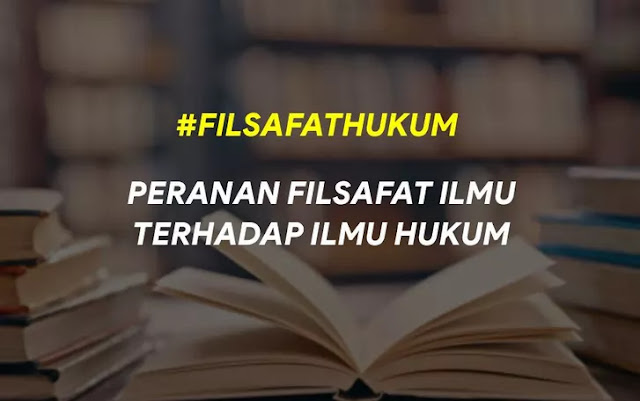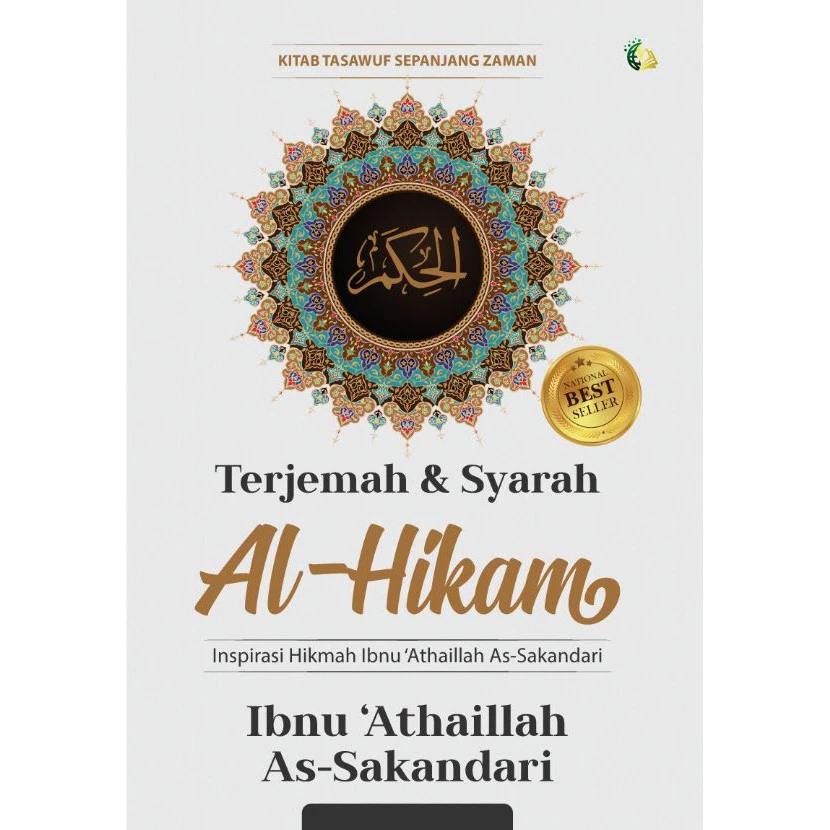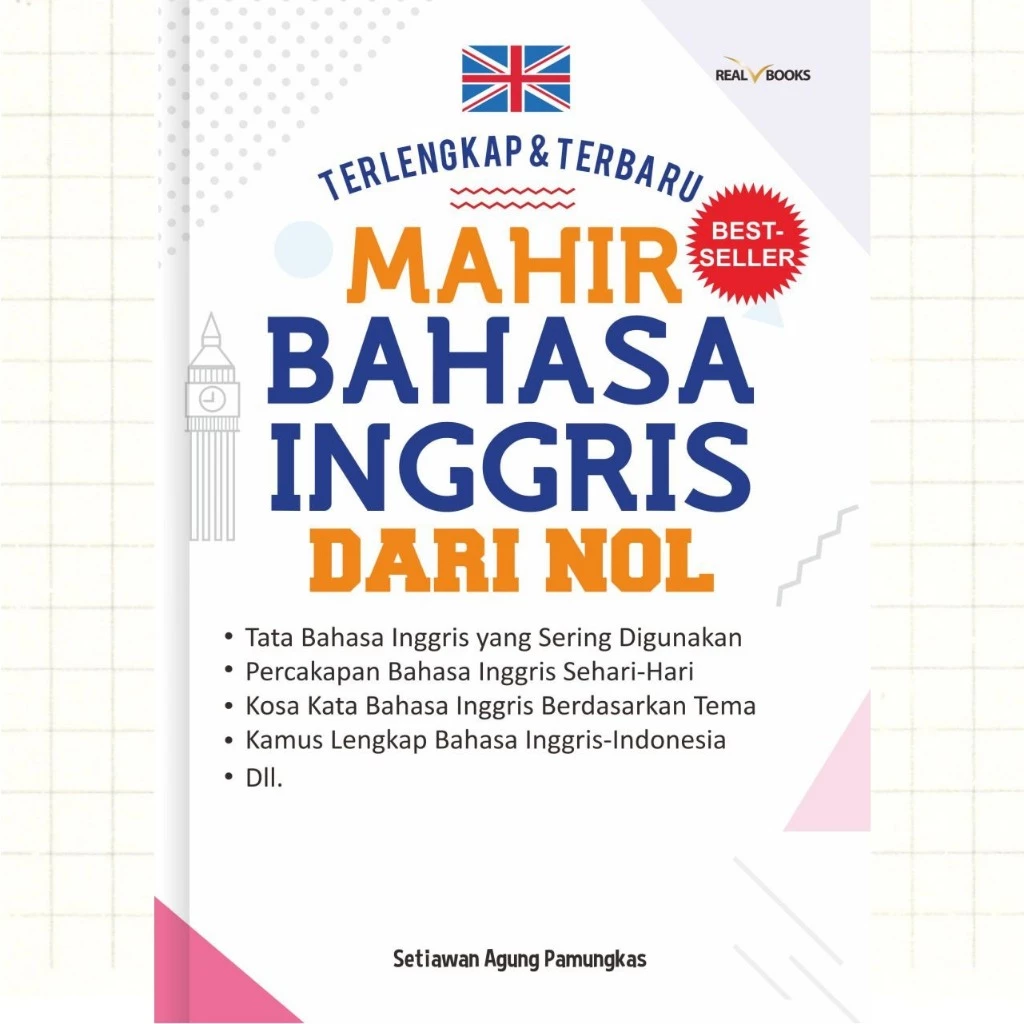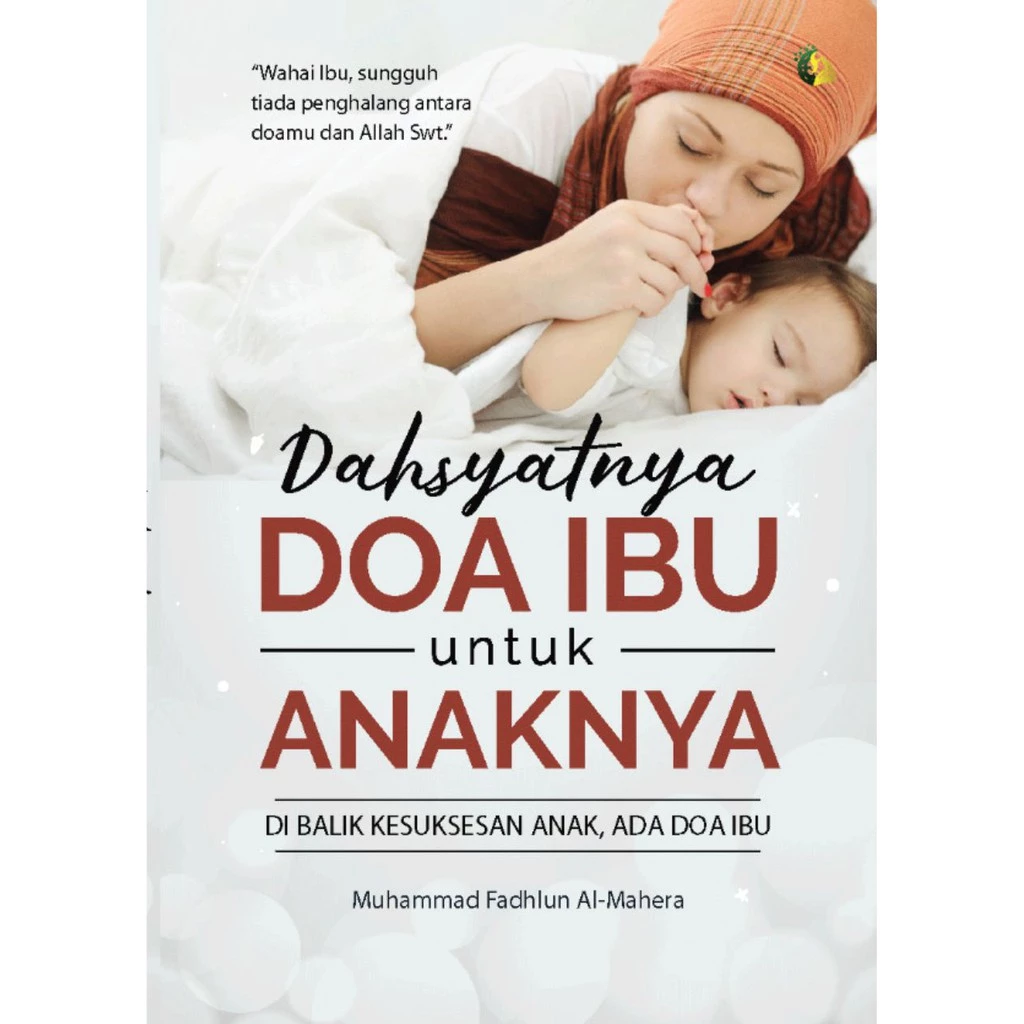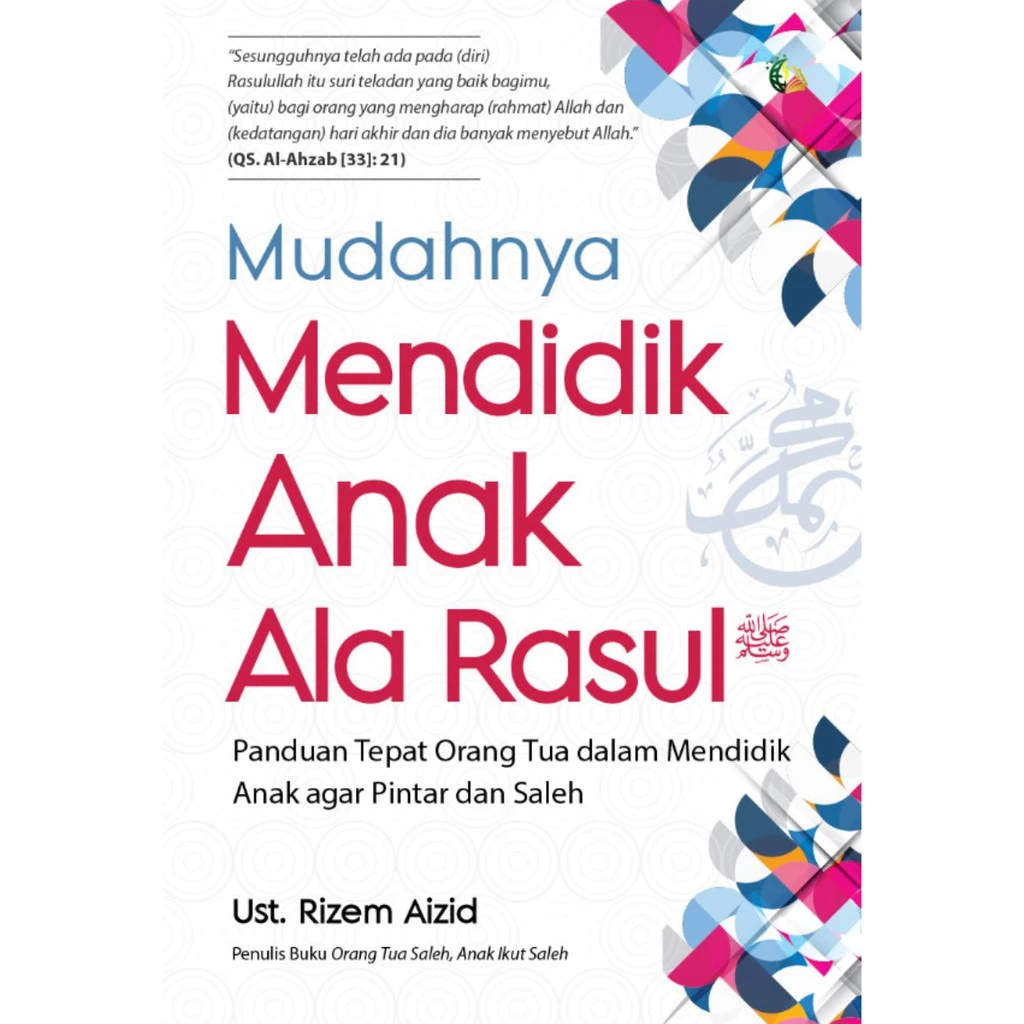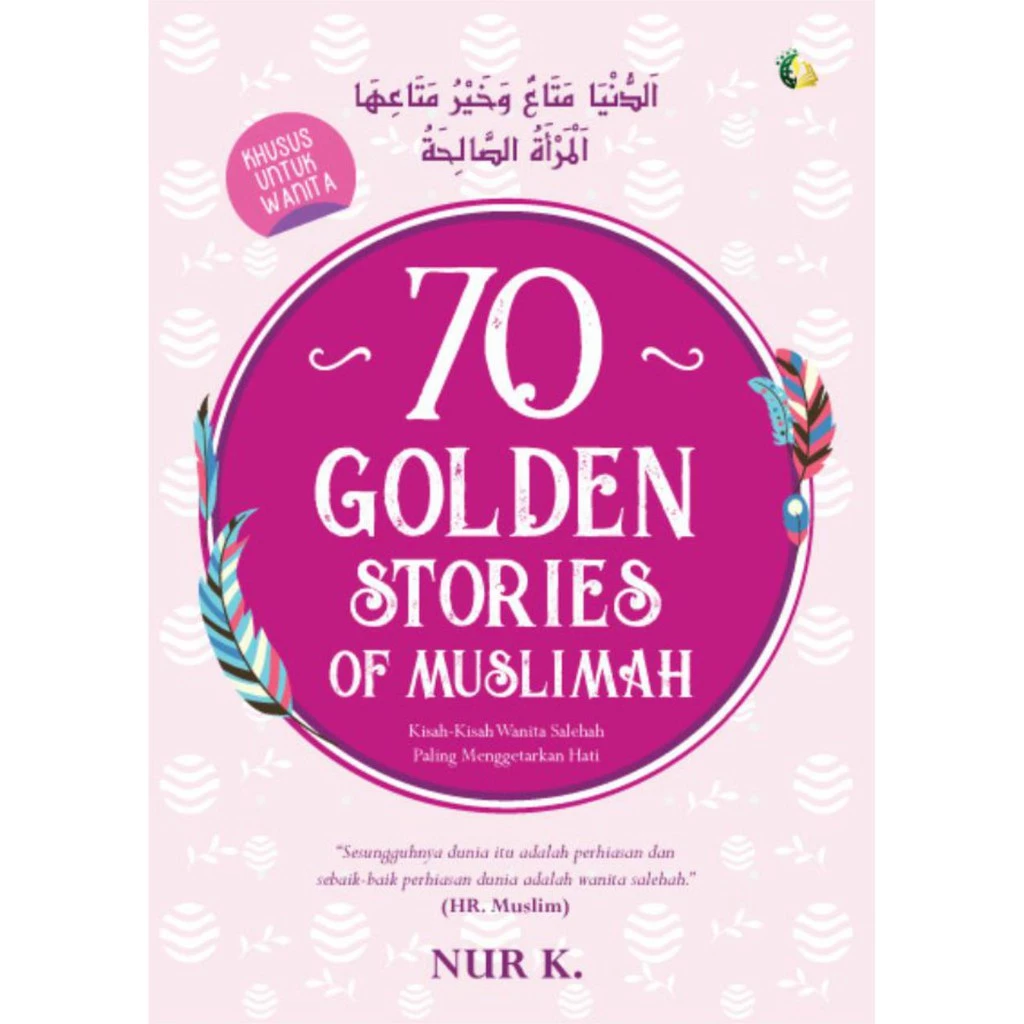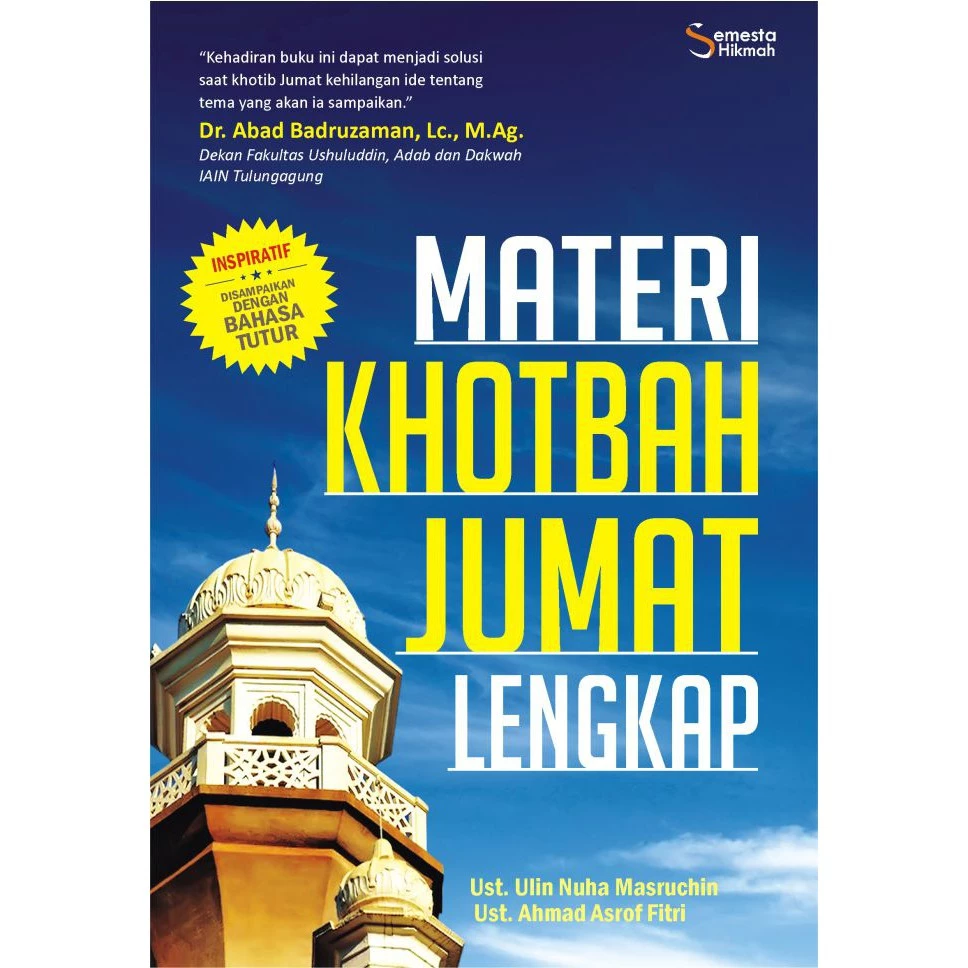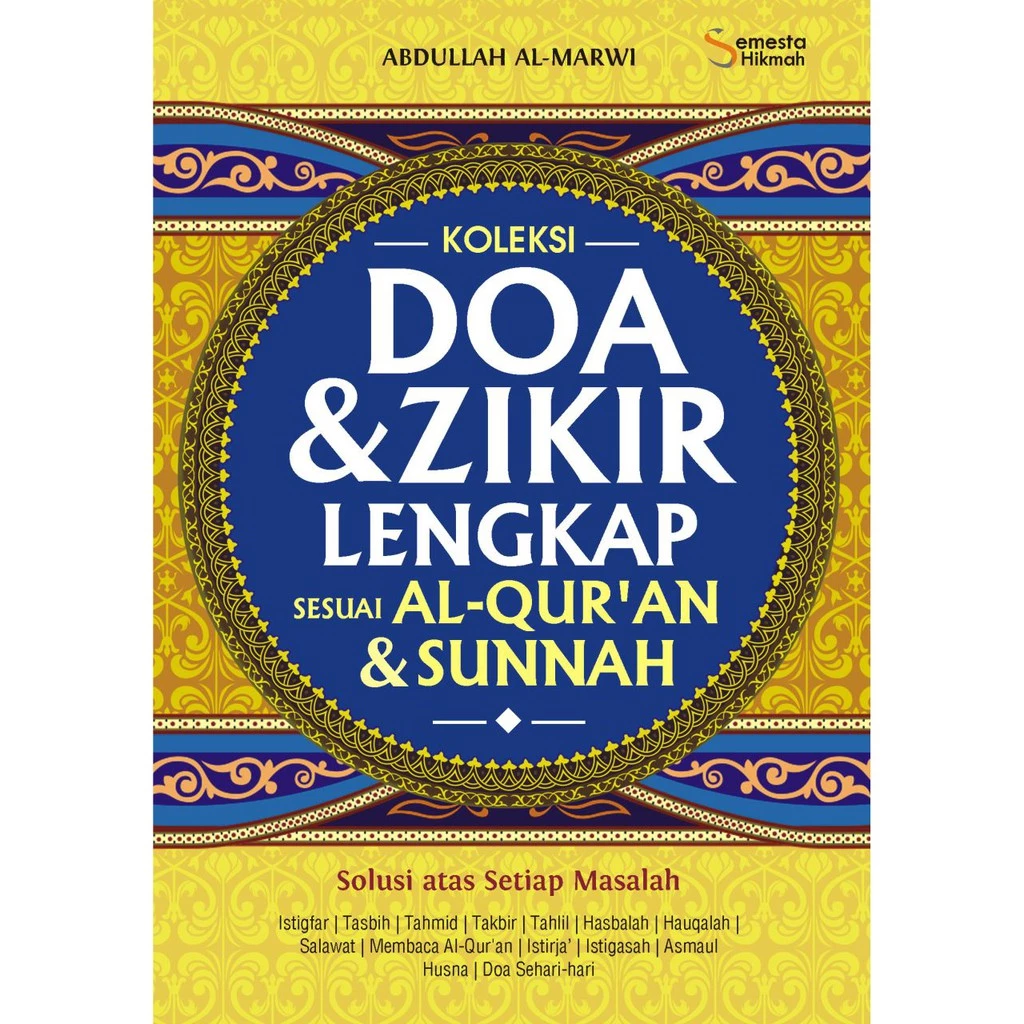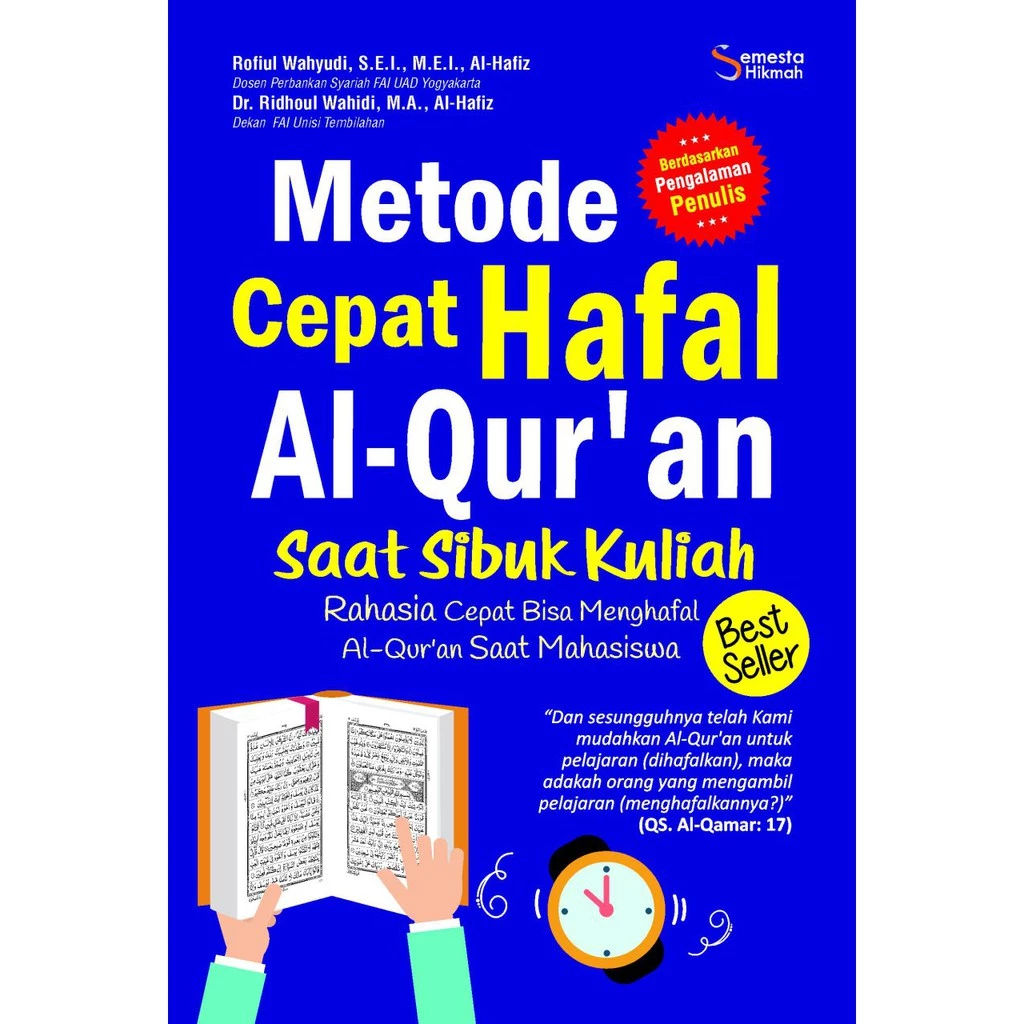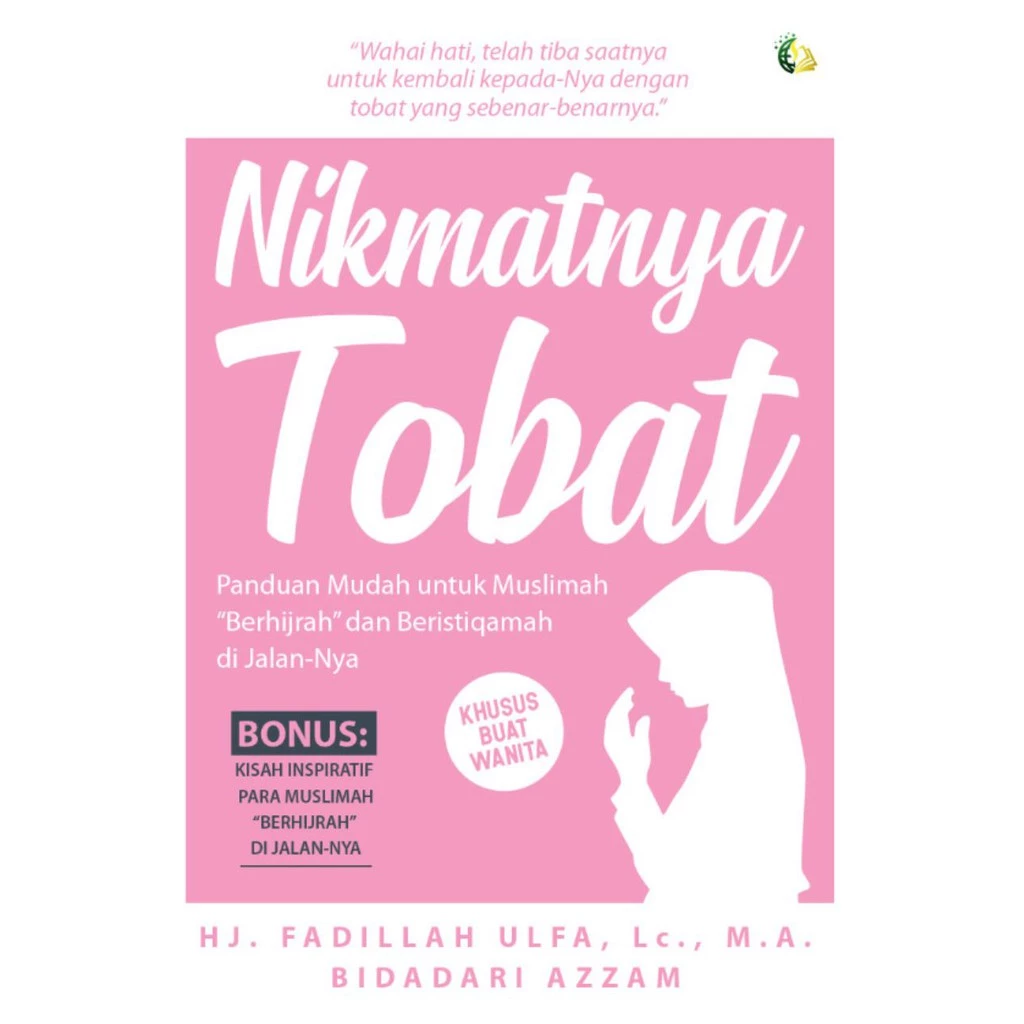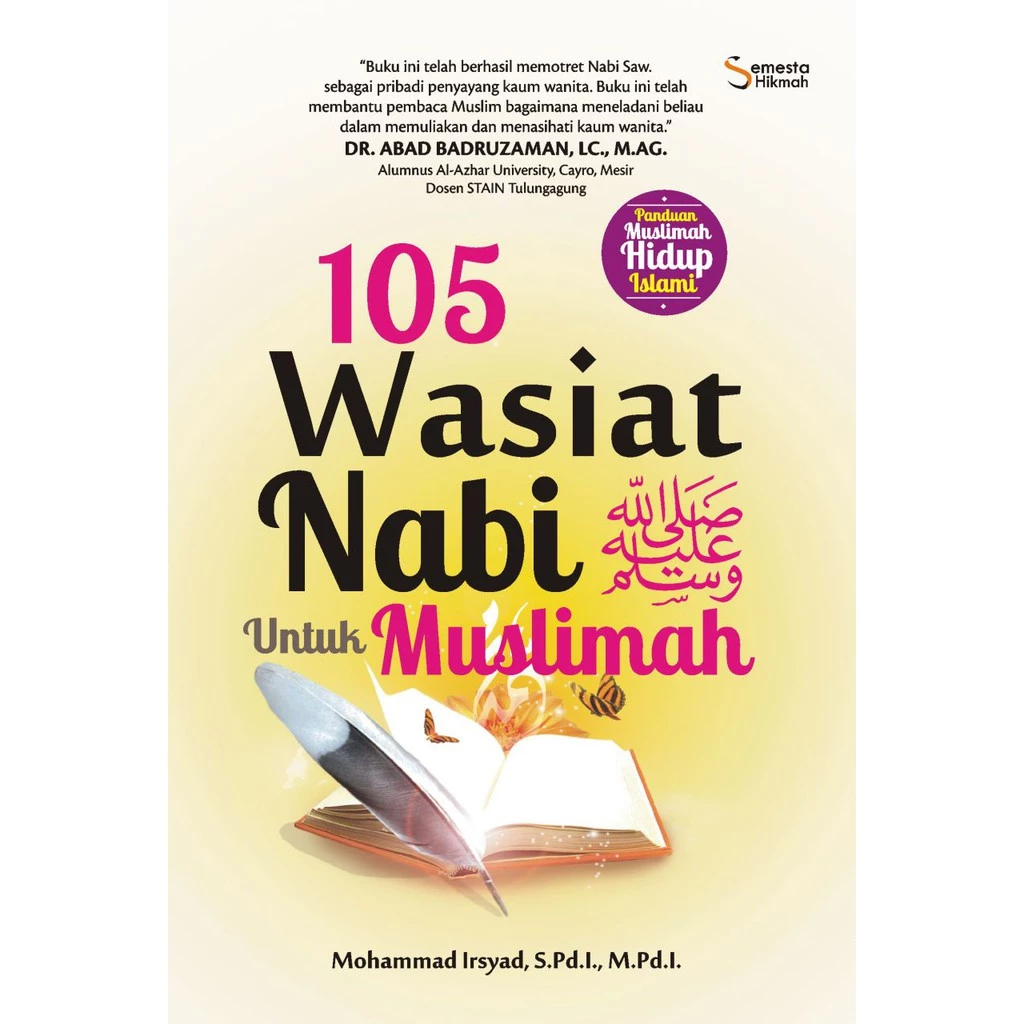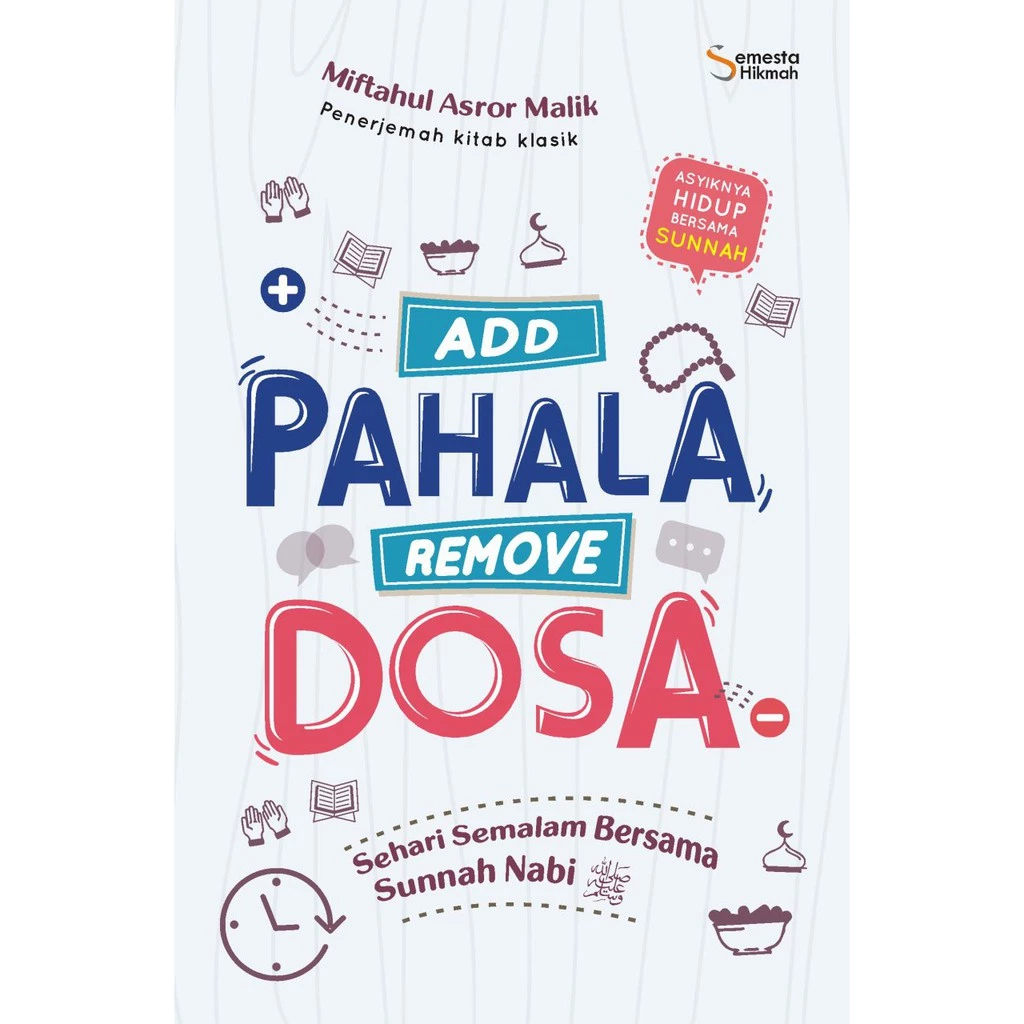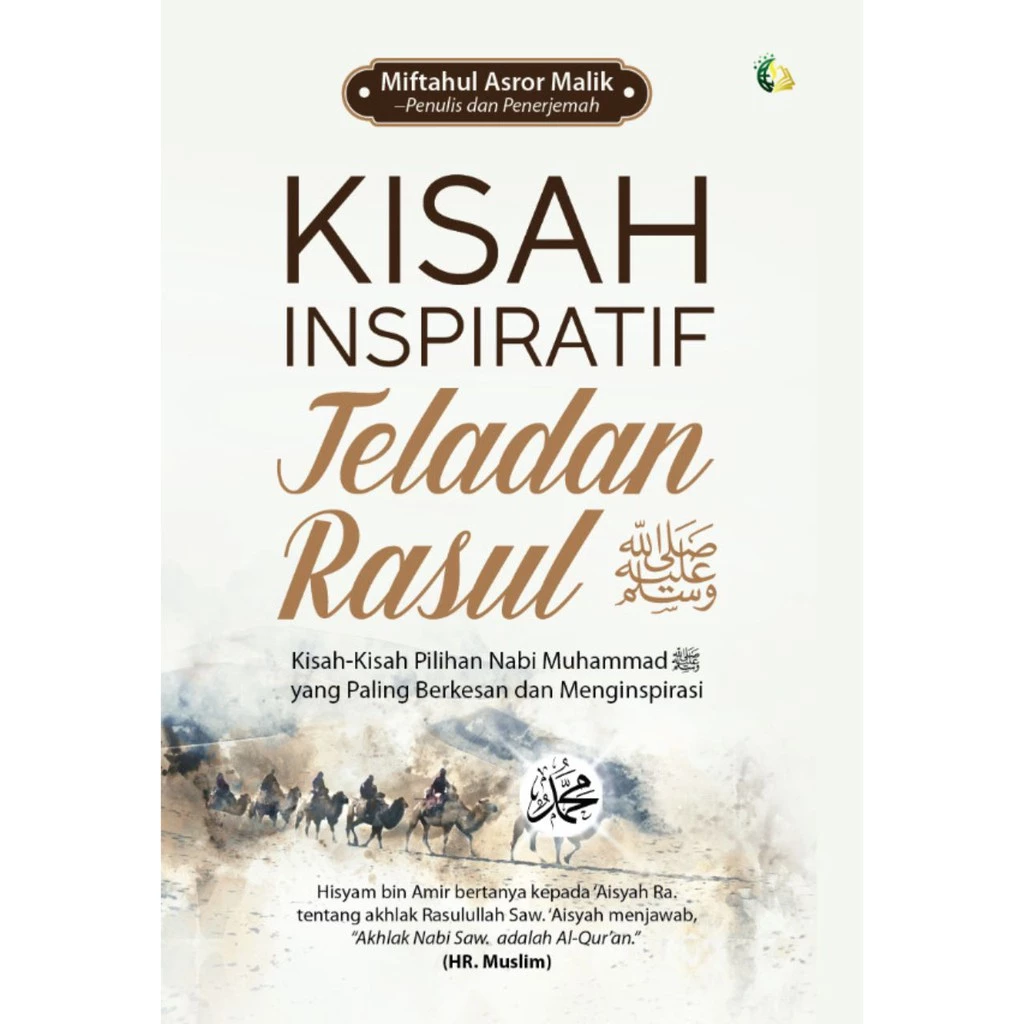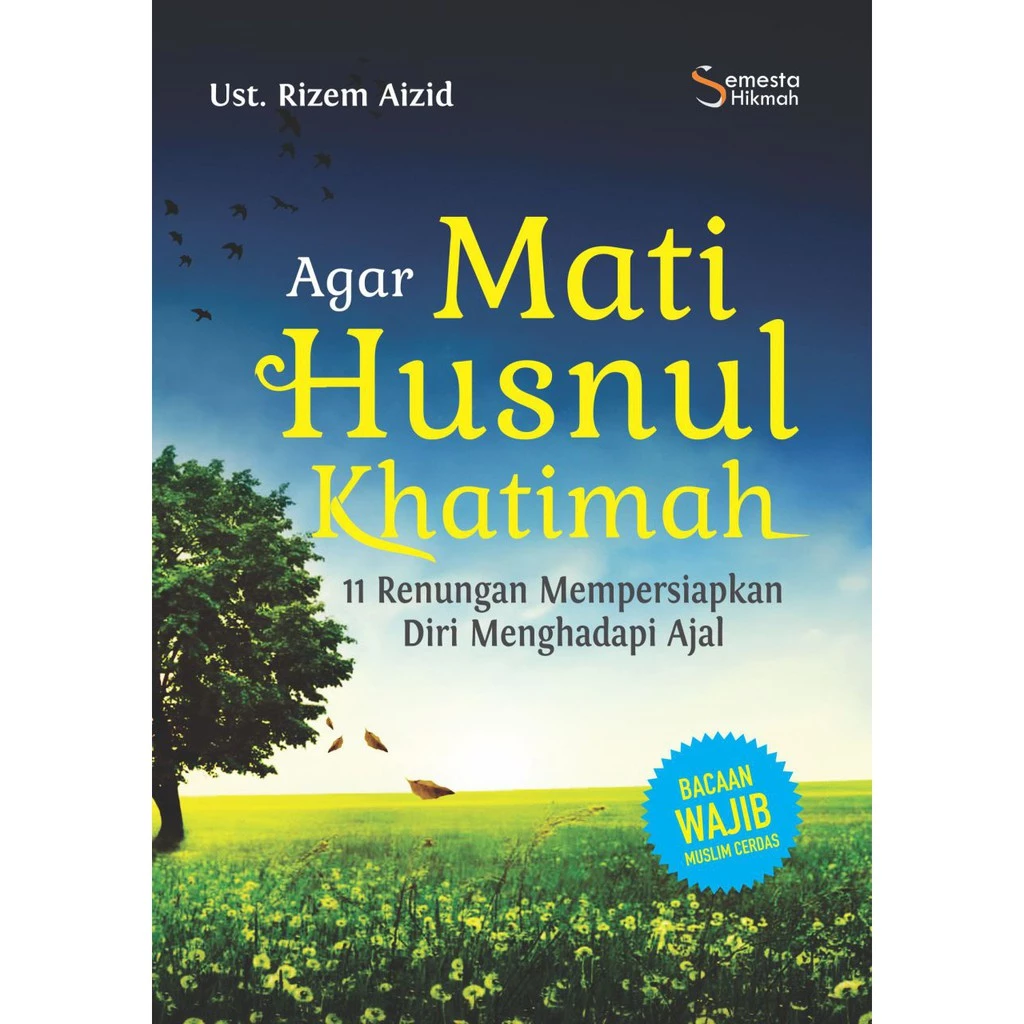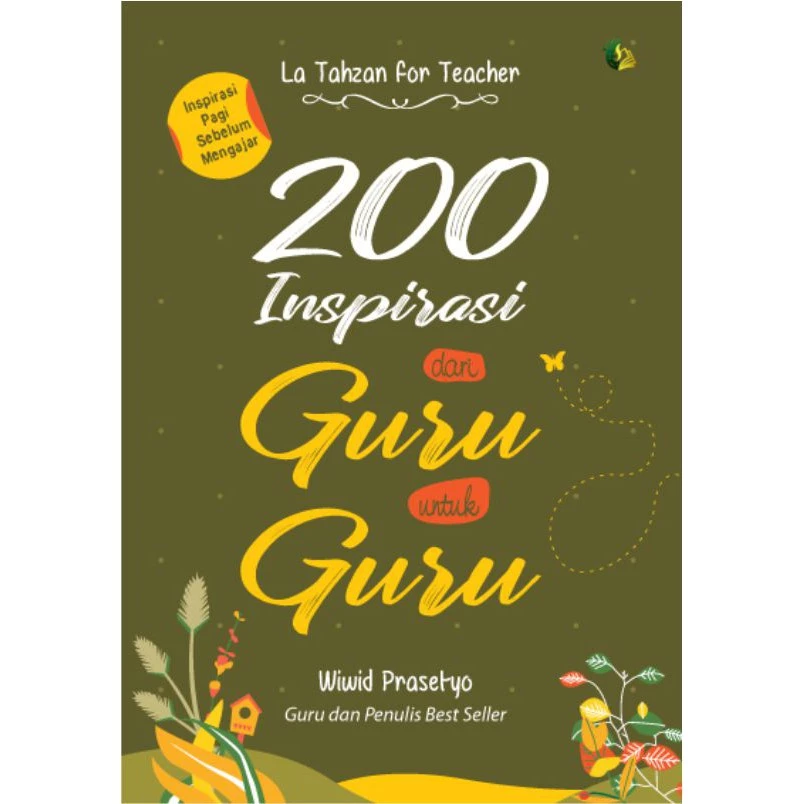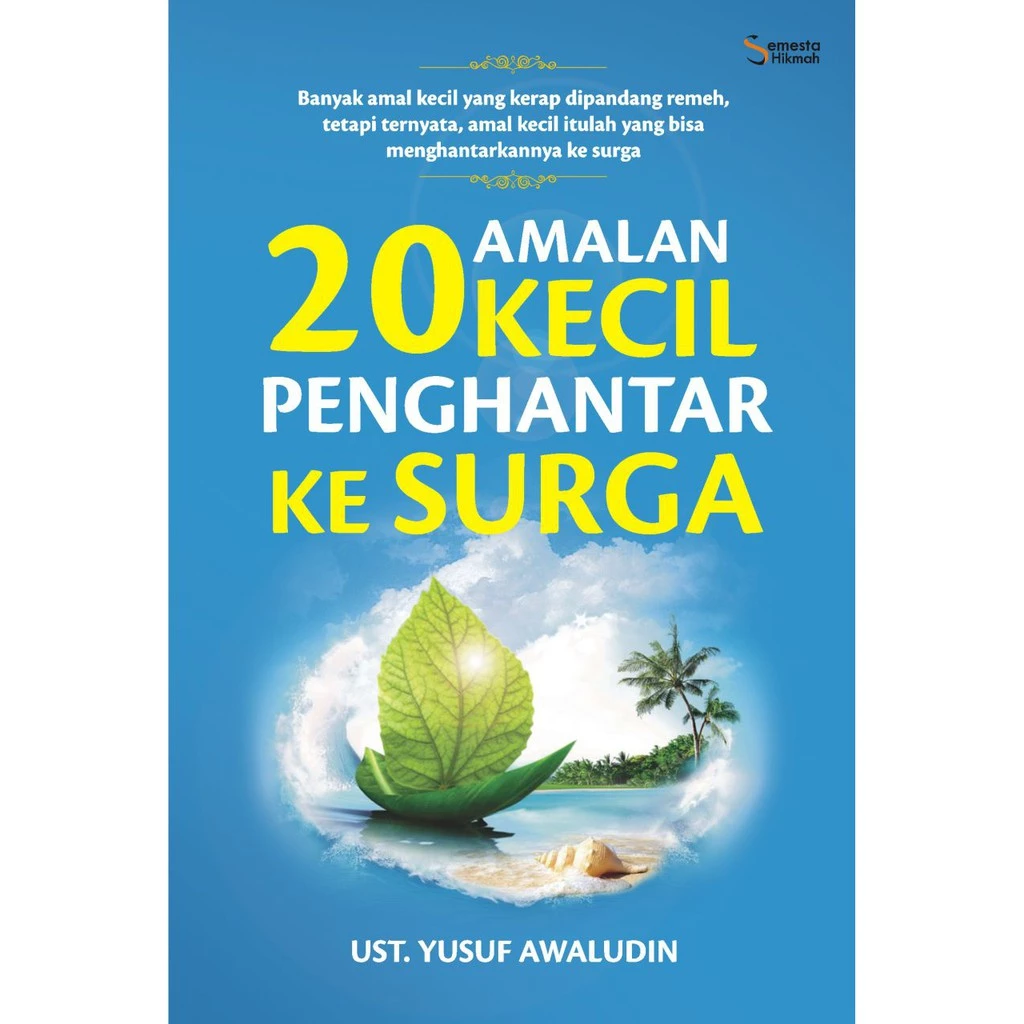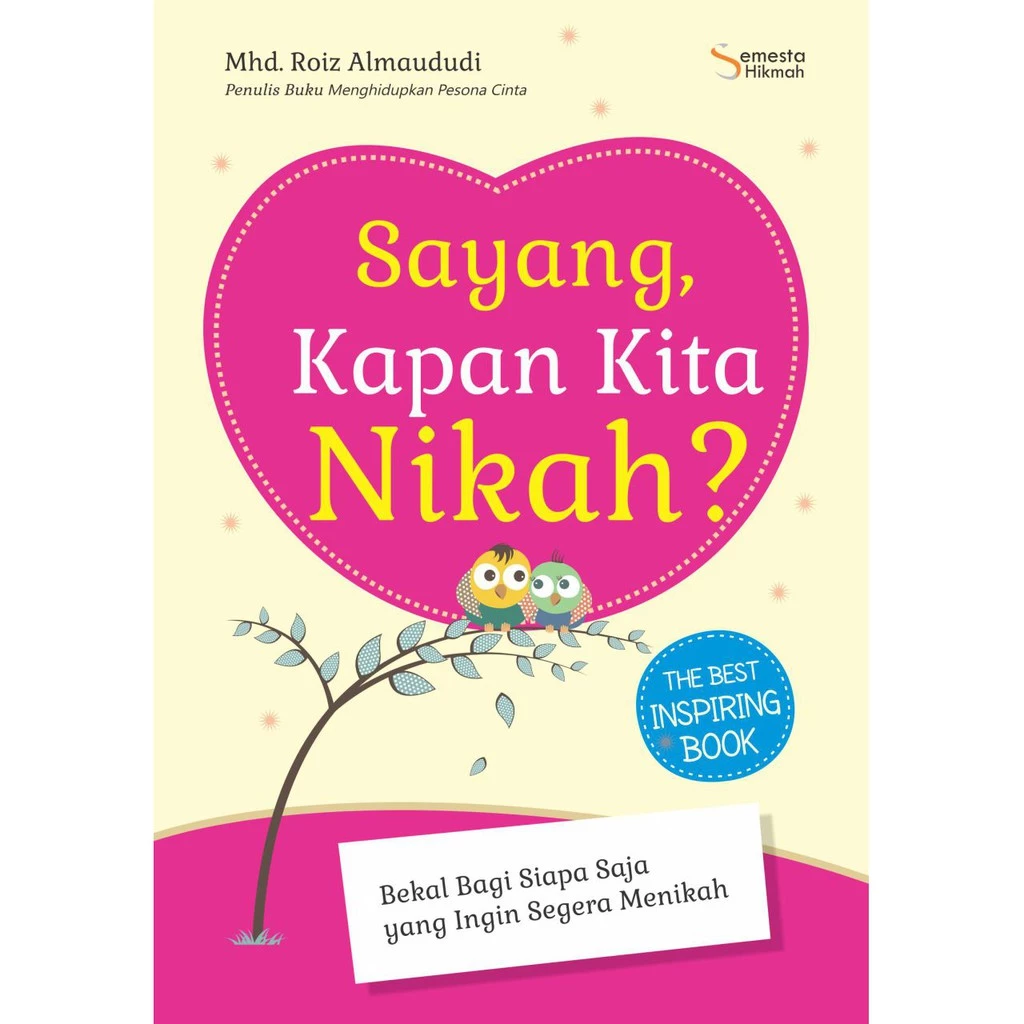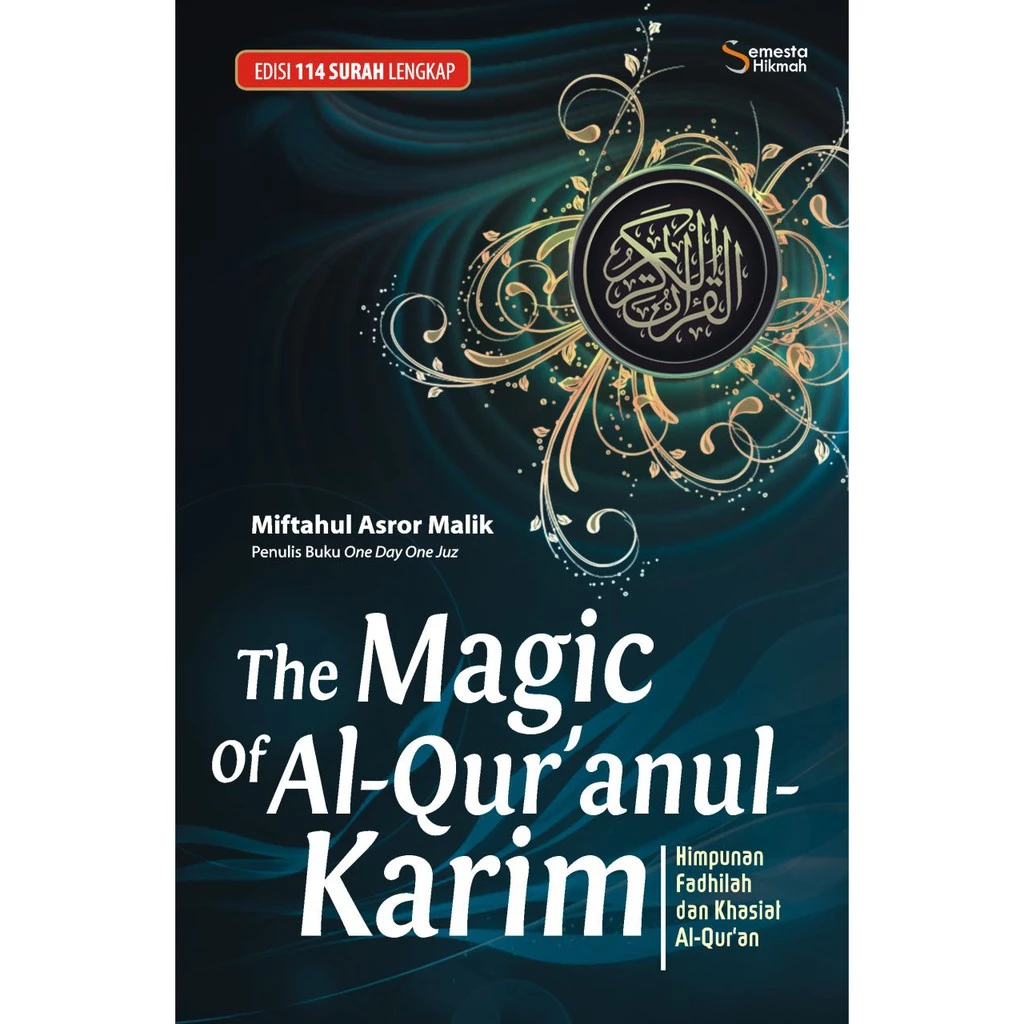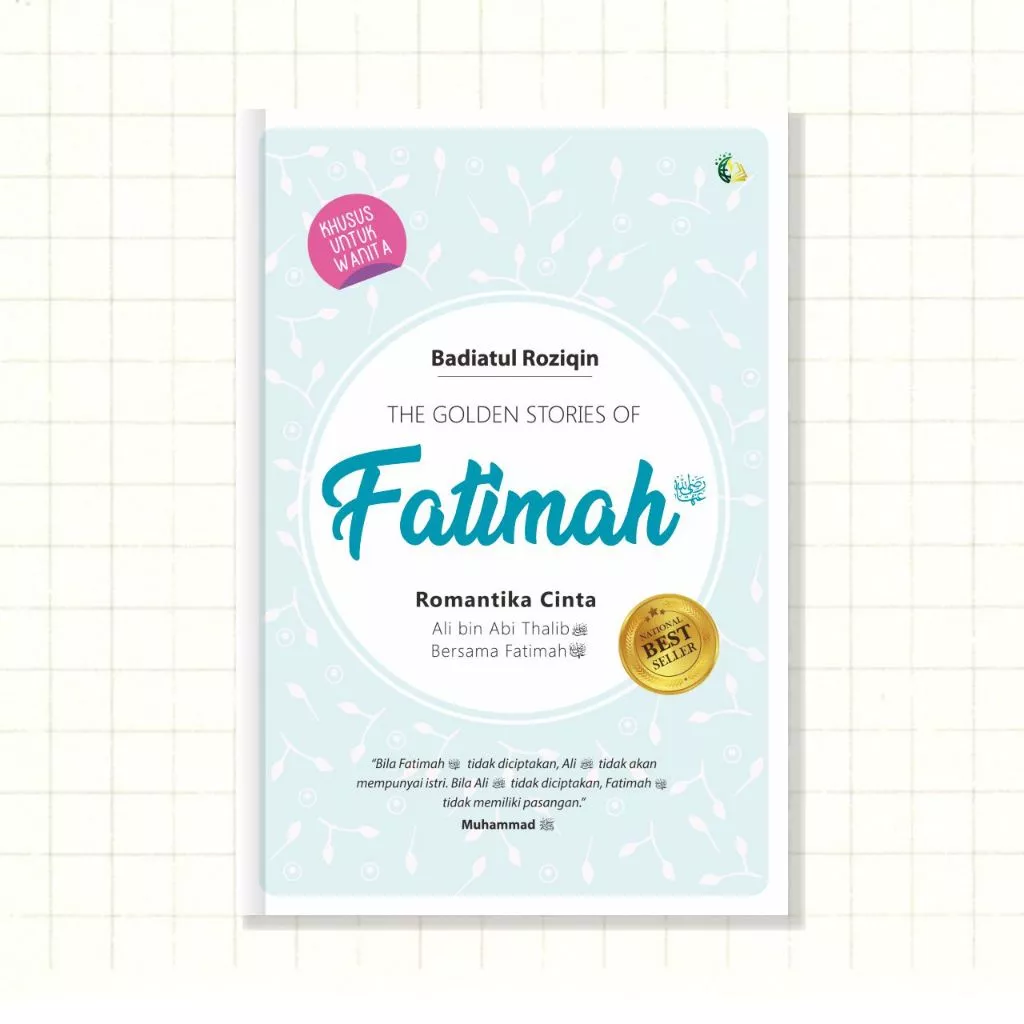Hukum Shalat Jumat Kurang dari 40 Orang

Hukum Shalat Jumat Kurang dari 40 Orang – Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai hukum mendirikan jamaah shalat Jumat yang pesertanya kurang dari 40 orang. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Berikut ulasannya.
Misal, ada sebuah desa yang penduduknya mayoritas muslim, tetapi jumlah penduduknya kurang dari 40 orang. Padahal kita tahu, shalat Jumat harus (minimal) berjumlah 40 orang mukim, jika kurang, maka shalat Jumat tersebut tidak sah.
Atau mungkin jumlah penduduknya lebih dari 40 orang, akan tetapi yang dapat membaca surat Al-Fatihah hanya 10 orang. Bagaimana pandangan Islam mengenai persoalan ini? Apakah penduduk desa tersebut masih berkewajiban mendirikan shalat Jumat? Jika boleh, apakah boleh mendirikan shalat Jumat kurang dari 40 orang?
Hukum Shalat Jumat Kurang dari 40 Orang
Seperti yang telah kita ketahui, ulama mazhab Hanafi memperbolehkan melaksanakan shalat Jumat kurang dari 40 orang. Jika demikian, bagaimana hukumnya jika kita taklid ke mazhab lain seperti Hanafi misalnya?
Baca juga:
- Niat dan Tata Cara Sholat Jumat Lengkap
- Tata Cara Shalat Qabliyah dan Ba’diyah Jumat
- 7 Syarat-syarat Khutbah Jumat Lengkap
Dalam Muktamar NU ke-2 di Surabaya, menjawab permasalahan mengenai penduduk desa yang lebih dari 40 orang, tetapi hanya 10 orang saja yang dapat membaca surat Al-Fatihah.
Apabila penduduk desa yang tidak bisa membaca Al-Fatihah itu disebabkan karena malas belajar (taqshir) maka mereka wajib mendirikan shalat Jumat dan bertaklid kepada Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi) dengan ketentuan harus menunaikan rukun dan syarat sesuai dengan mazhab Hanafi pula. Jadi harus satu paket, tidak boleh dicampur-campur antara mazhab satu dengan mazhab yang lain.
Misal, untuk jumlah jamaah shalat jimat mengambil mazhab Hanafi (boleh kurang dari 40 orang), sedangkan rukun dan syarat shalat Jumatnya menggunakan mazhab Syafi’i. Jika demikian, maka hukumnya tidak boleh. Akan tetapi wajib baginya menggunakan satu mazhab dalam satu paket ibadah (ibadah shalat Jumat).
Hal ini juga berlaku untuk shalat. Tidak boleh mencampur dua mazhab dalam satu ibadah. Contoh, wudhu menggunakan mazhab Syafi’i, sedangkan cara salatnya menggunakan mazhab Maliki. Kami tegaskan, hal ini tidak boleh.
Dalilnya
Dijelaskan dalam kitab Al-Fatwa al-Kubra al-Fiqhiyah[1], bahwa orang-orang yang buta huruf (Al-Qur’an), jika disebabkan karena teledor dari belajar, maka shalat Jumatnya tidak sah, namun jika karena bukan faktor keteledoran, misal mualaf, maka wajib baginya melaksanakan shalat Jumat, dan sah pula hukumnya meskipun buta huruf.
Dalam kitab I’anah al-Thalibin[2], ada penjelasan bahwa “Sebagaimana pendapat yang tidak bertentangan qaul qadim dalam permasalahan jumlah. Yang pertama, jumlah minimal adalah empat orang,…(ilaakhirihi) yang kedua, dua belas orang. Bolehkah mengikuti salah satu dari pendapat tersebut? Jawabannya boleh, karena pendapat tersebut merupakan pendapat dari Imam yang telah dibela dan diunggulkan oleh para pengikutnya.
Dari qaul qadim tersebut akhirnya menjawab tanda tanya masyarakat mengenai persoalan shalat Jumat para pegawai kantoran, pabrik, atau yang sejenisnya. Bagaimana hukumnya shalat Jumat bagi para pendatang? Maksudnya adalah bagi masyarakat luar desa, di sekolah, atau bahkan TKI TKW yang berada di Korea, China, jepang, dll.
Berikut jawabannya :
Yang pertama, perlu Anda ketahui bahwa orang yang berada di luar daerah atau sedang bepergian (musafir) tidak wajib mendirikan shalat Jumat.
Shalat Jumatnya musafir dan budak sama hukumnya dengan anak-anak, tidak sah apabila di posisikan sebagai syarat “mukim” (menetap di daerahnya) pada shalat Jumat.
Apabila mengambil qaul qadim dari mazhab Syafi’i, boleh bagi mereka (pegawai kantor, pabrik, atau anak-anak sekolah) mendirikan shalat Jumat, tetapi dengan syarat harus mengajak minimal 4 orang mukim untuk ikut serta melaksanakan shalat Jumat.
Apabila mengambil hukum dari mazhab Hanafi, boleh bagi mereka mendirikan shalat Jumat tanpa harus mengajak orang mukim sekalipun, tetapi dengan konsekuensi harus mengikuti syarat dan rukun sesuai aturan mazhab Hanafi, mulai dari wudunya, salatnya, serta rukun-rukun lainnya.
Itulah pembahasan mengenai Hukum Shalat Jumat Kurang dari 40 Orang, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahu A’lam
[1] Ibnu Hajar Al-Haitami, Al-Fatwa al-Kubra al-Fiqhiyah, (Beirut: Dar al-Fakr). Jilid I, h. 273.
[2] Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I’anah al-Thalibin (Semarang: Thaha Putra). Jilid II, h. 58-59.