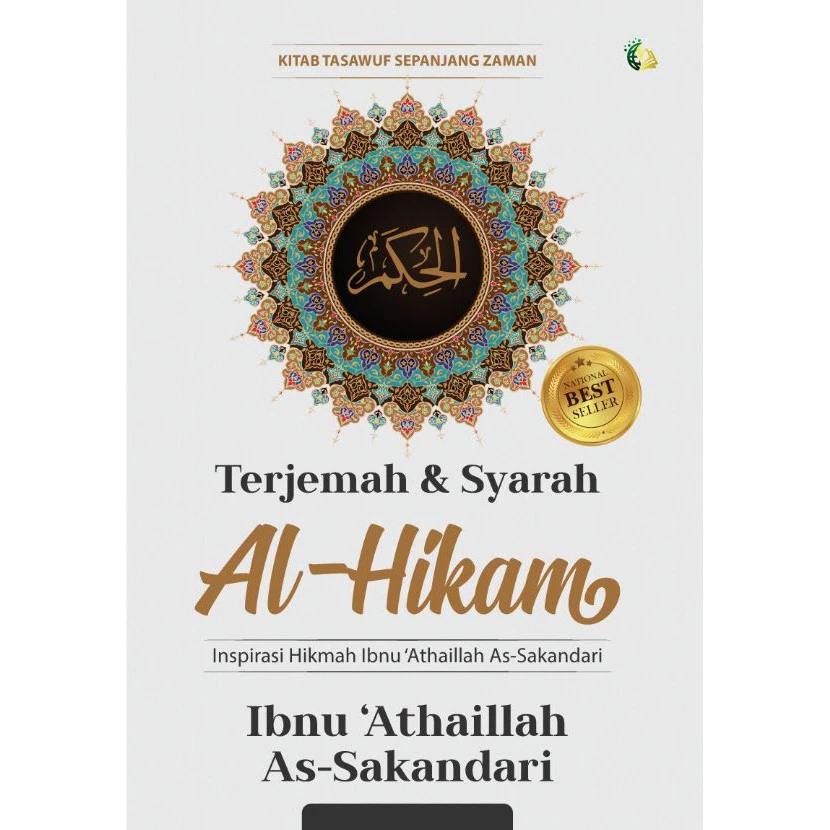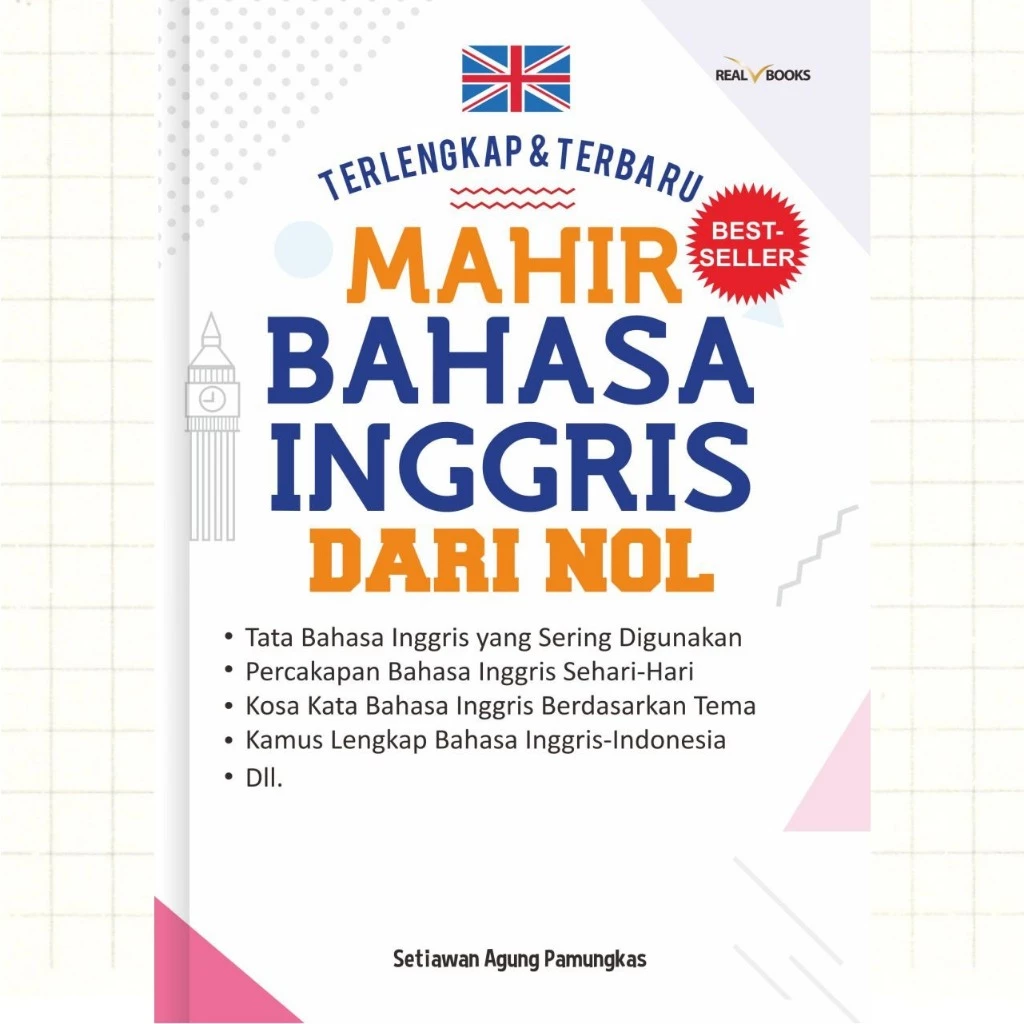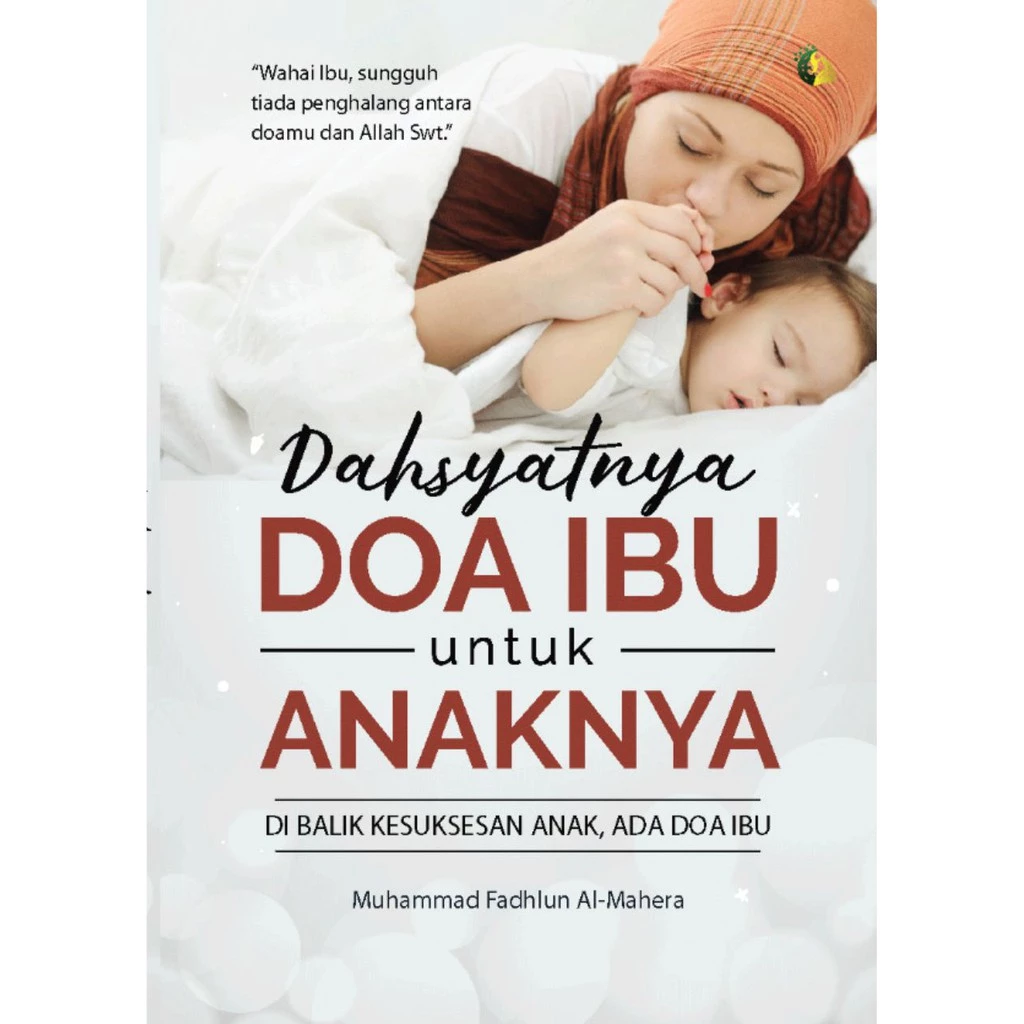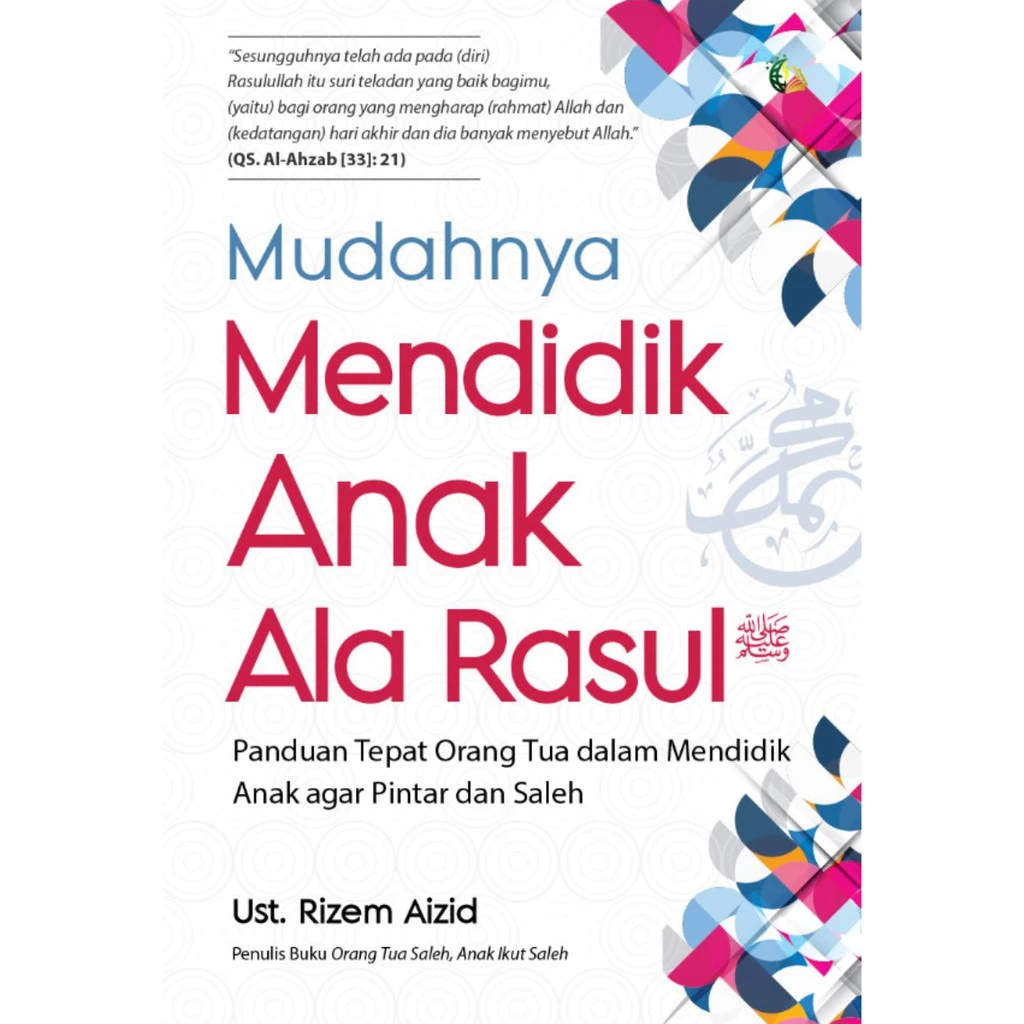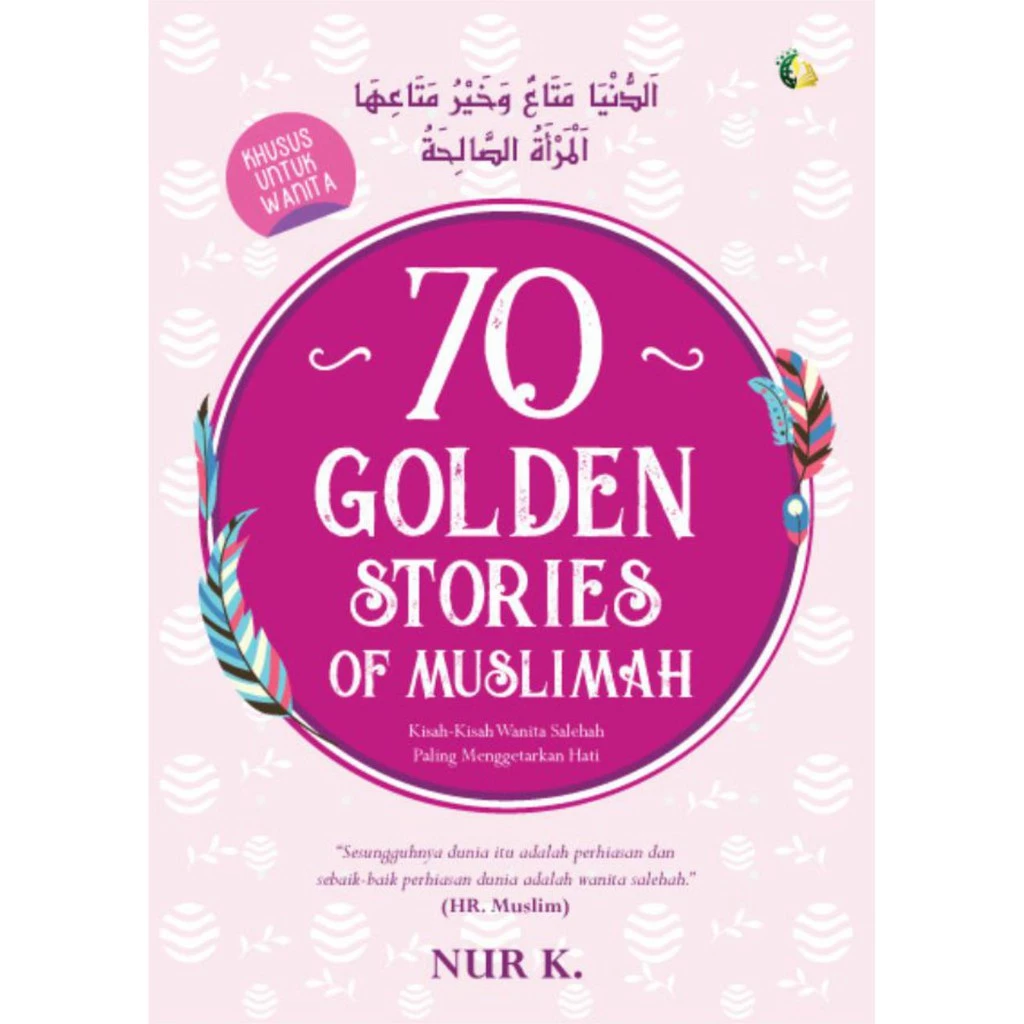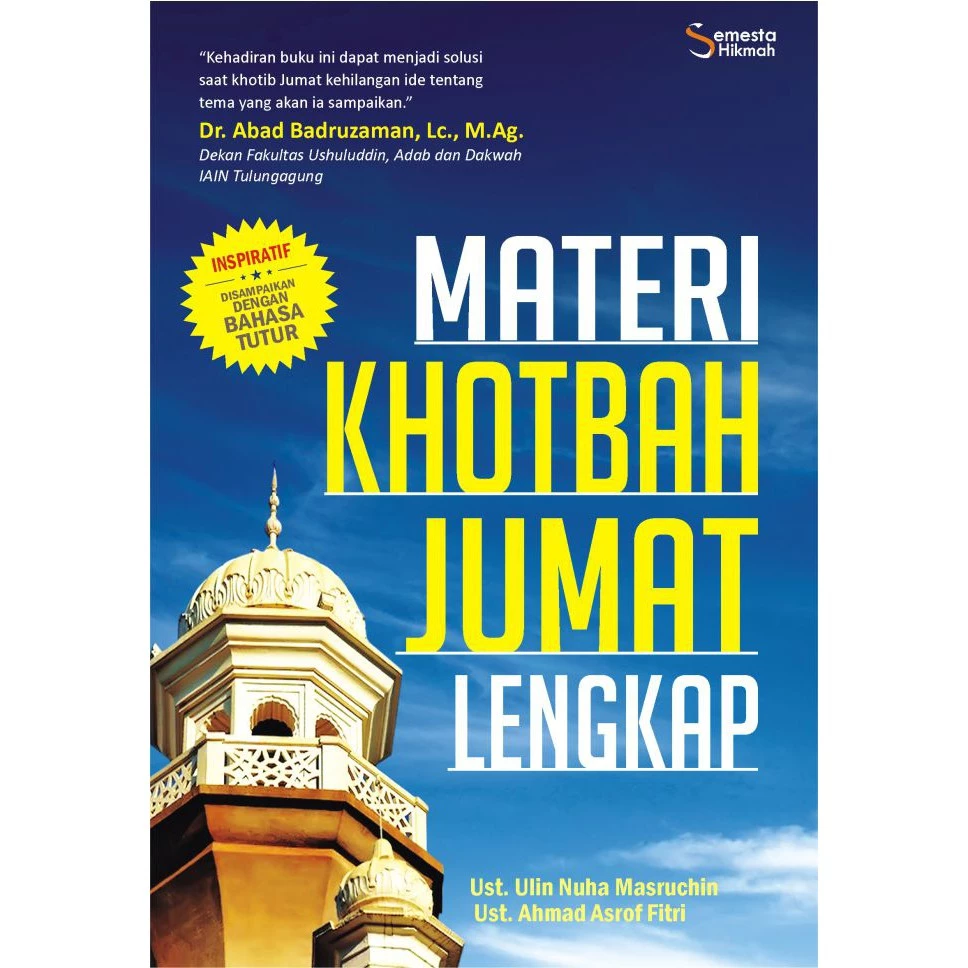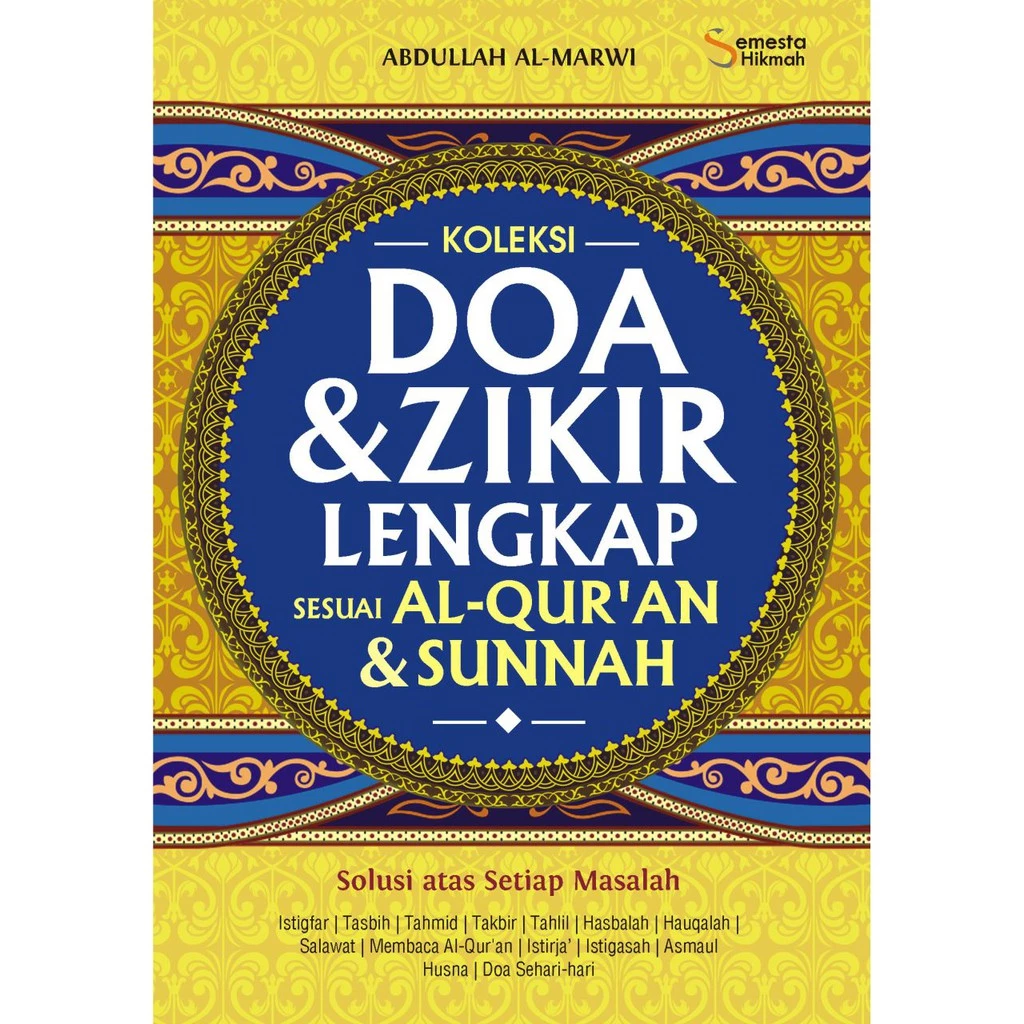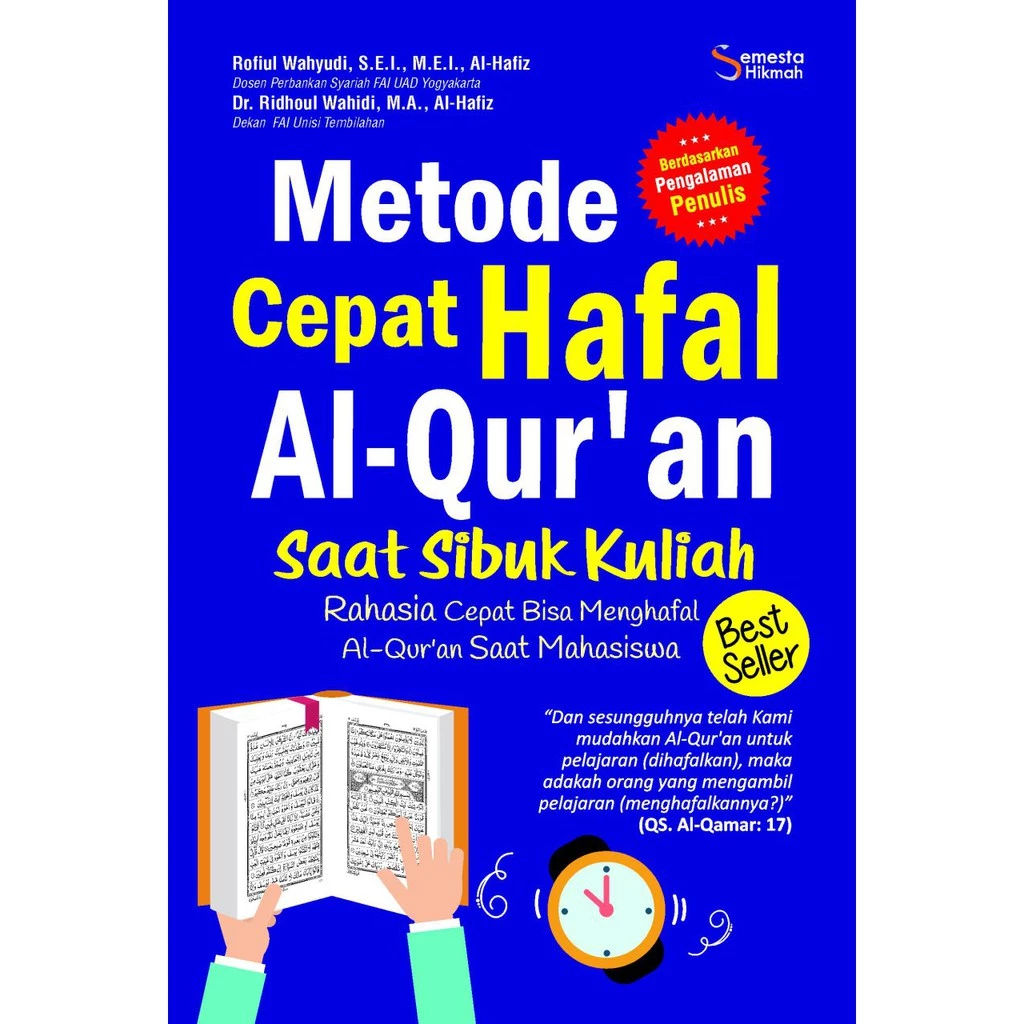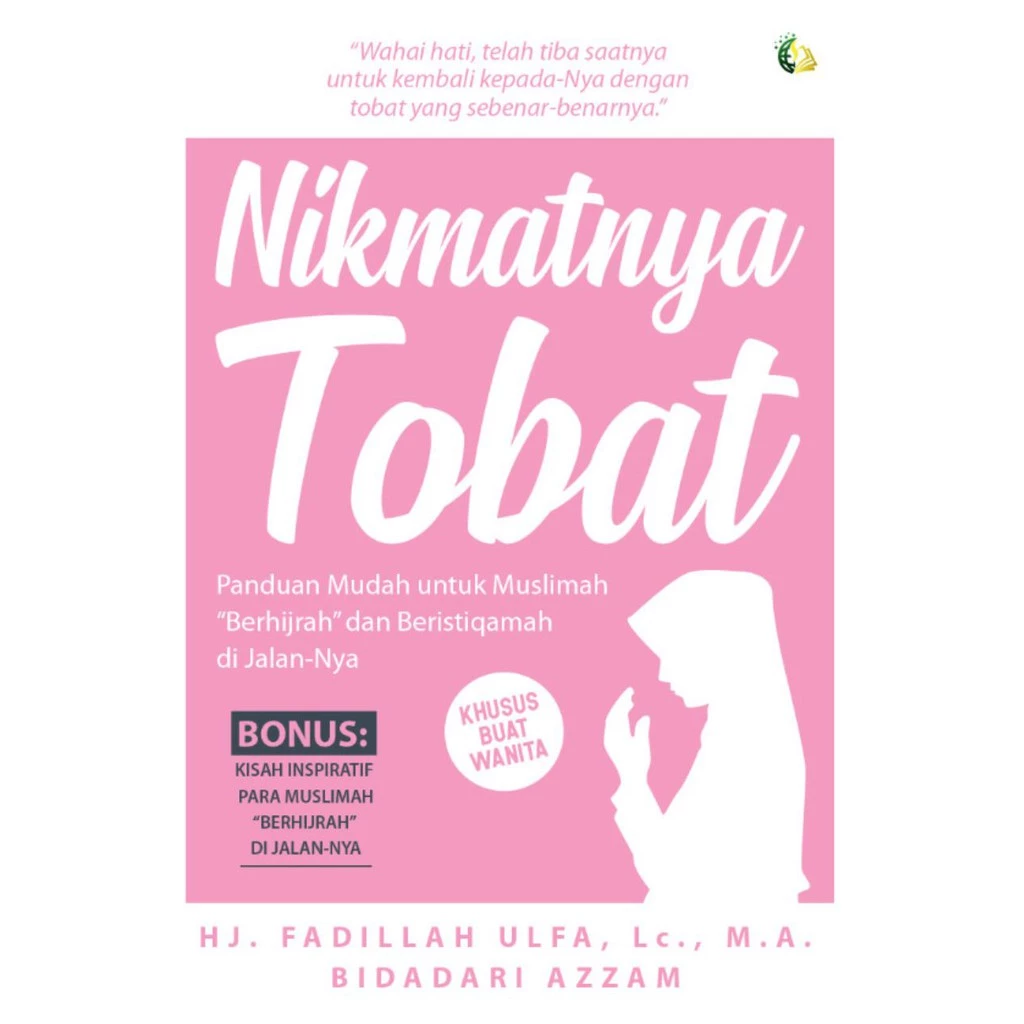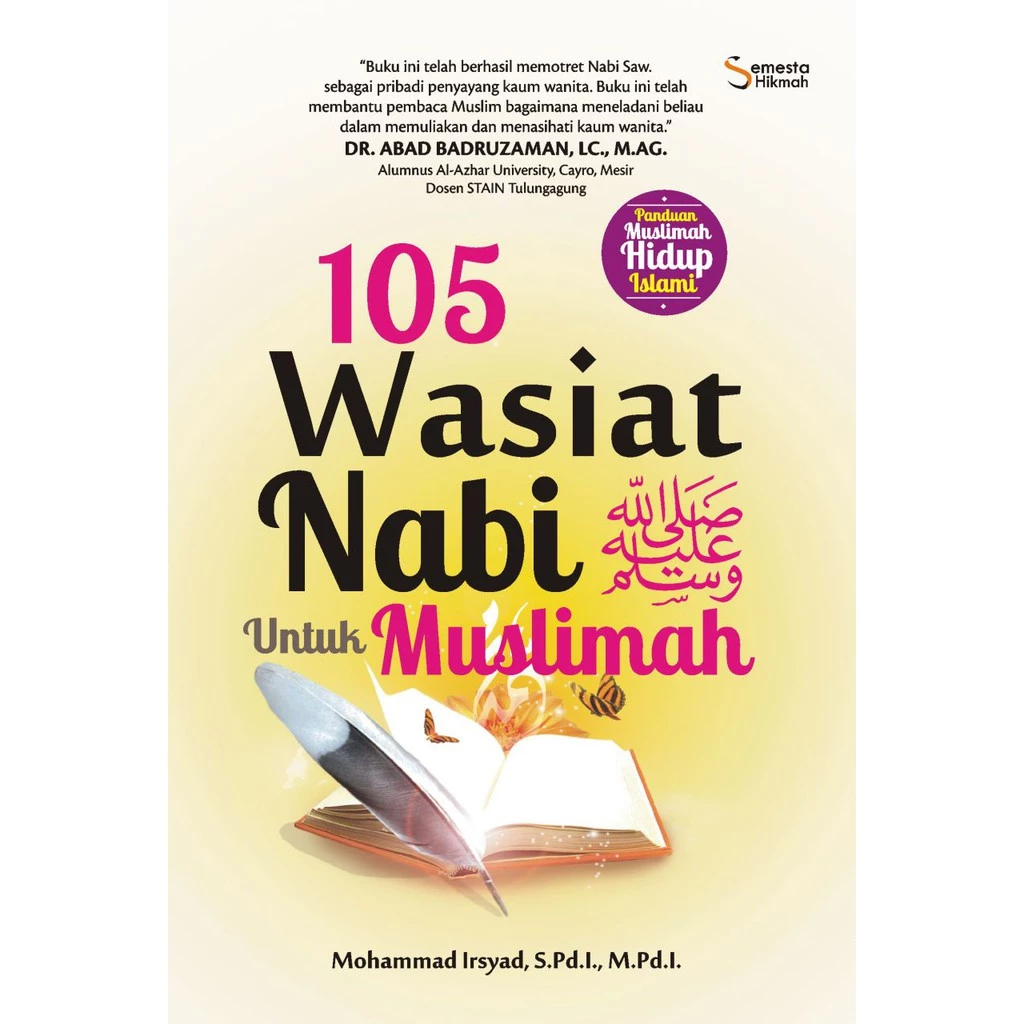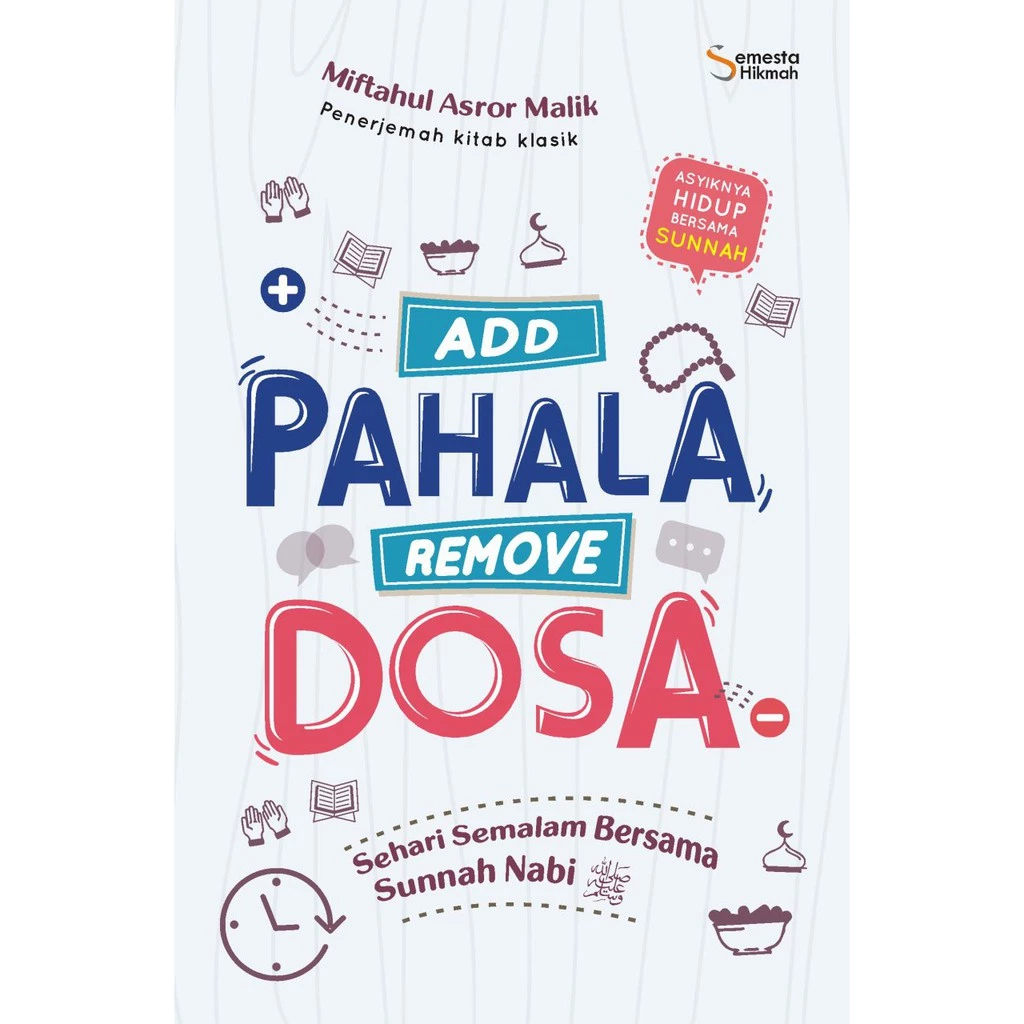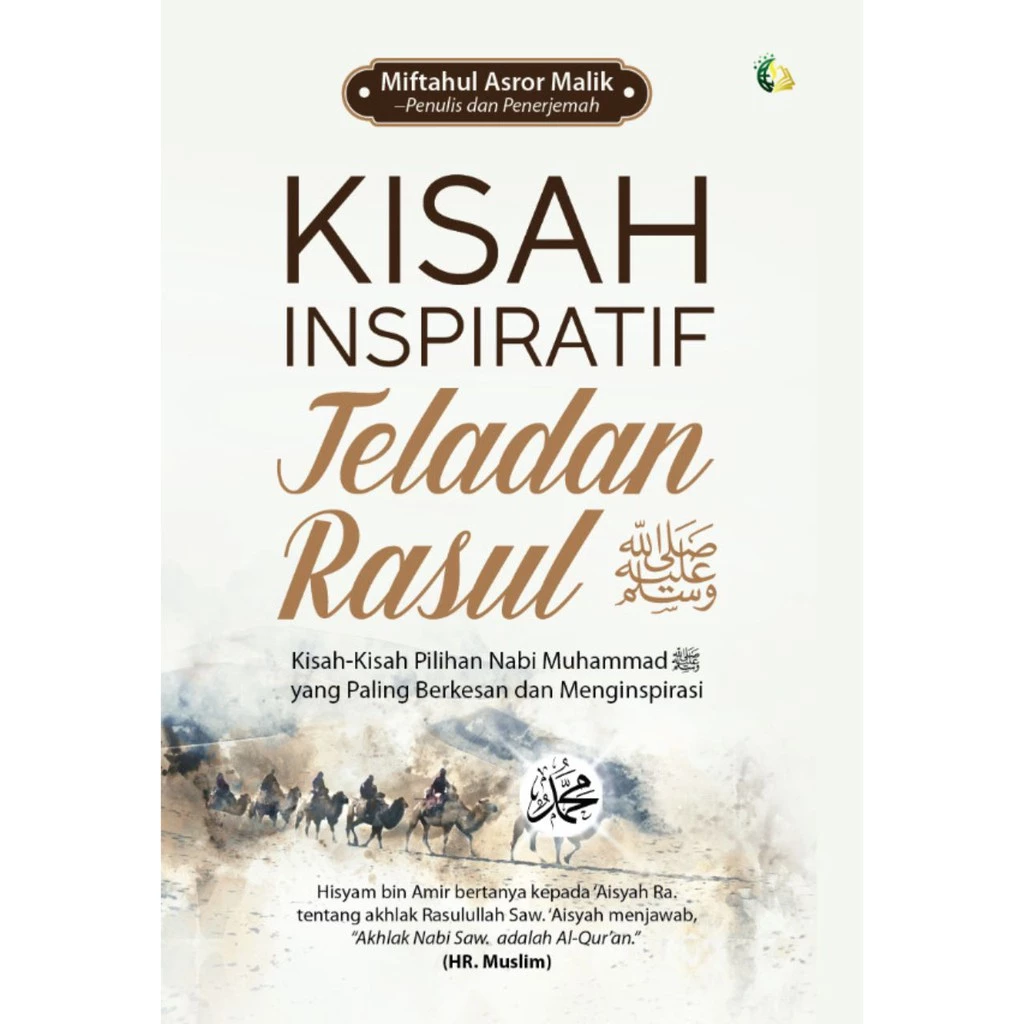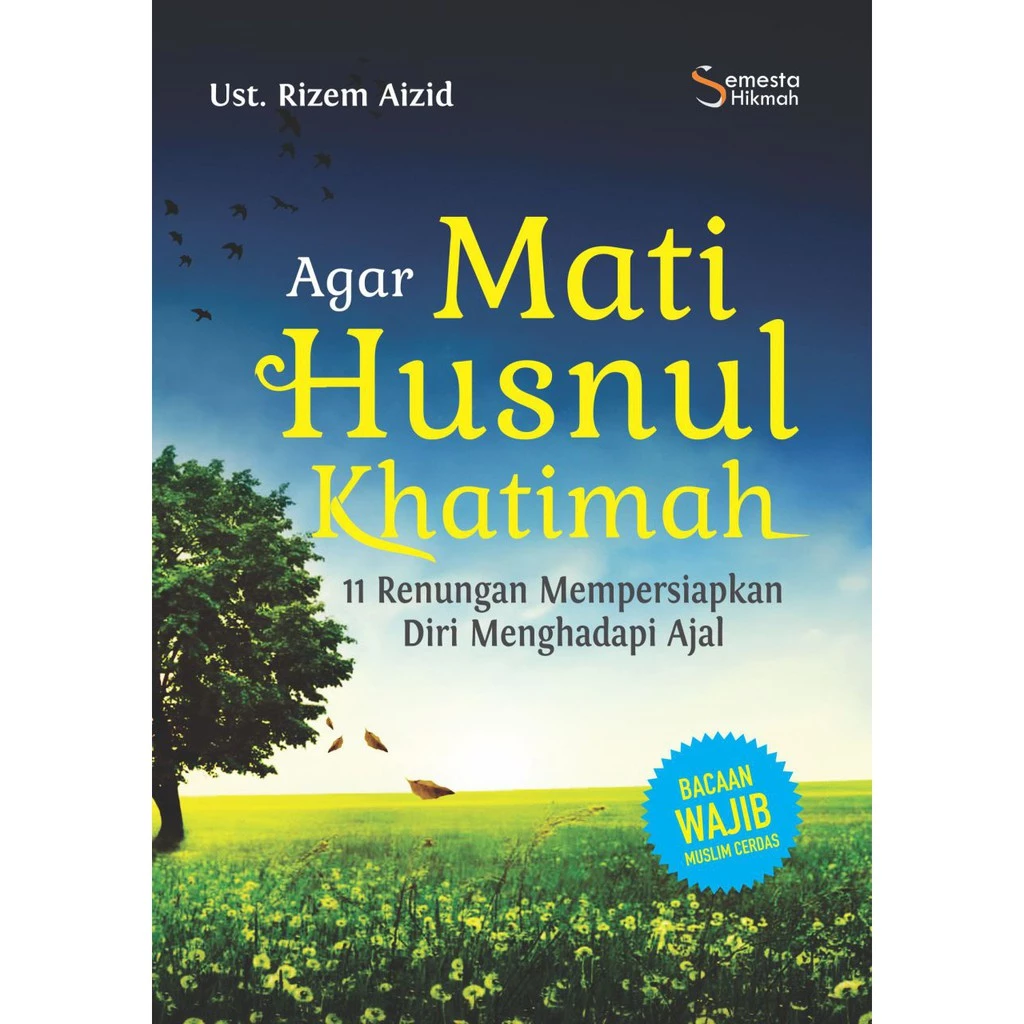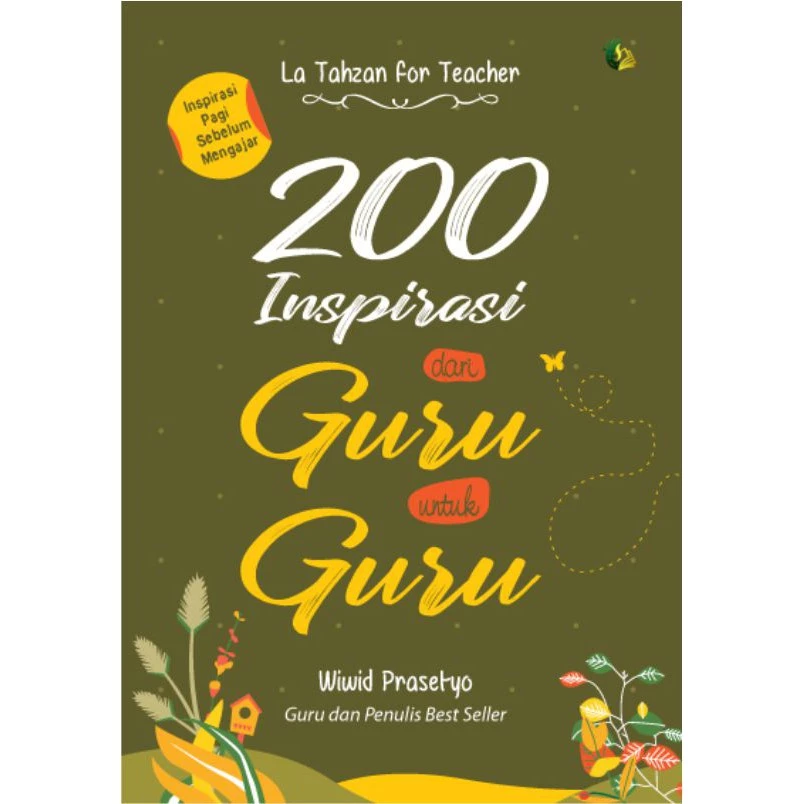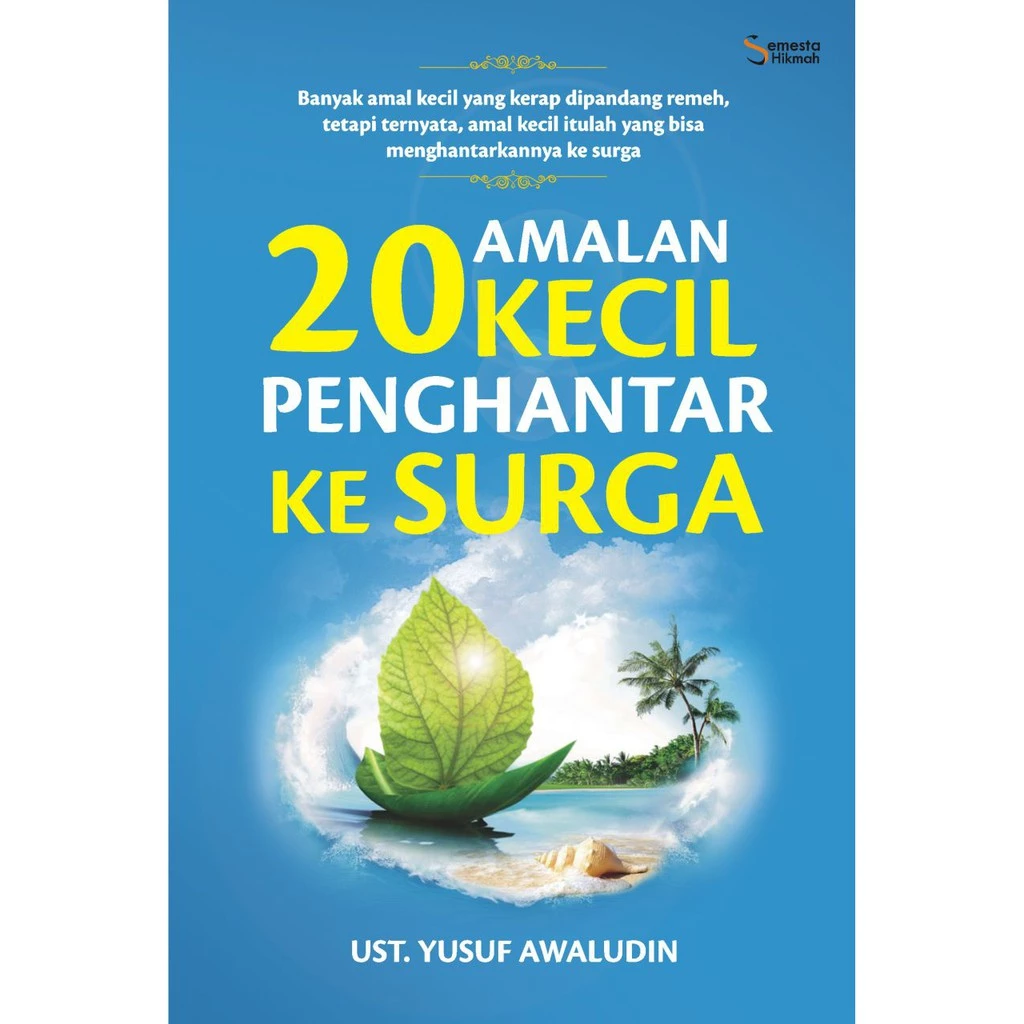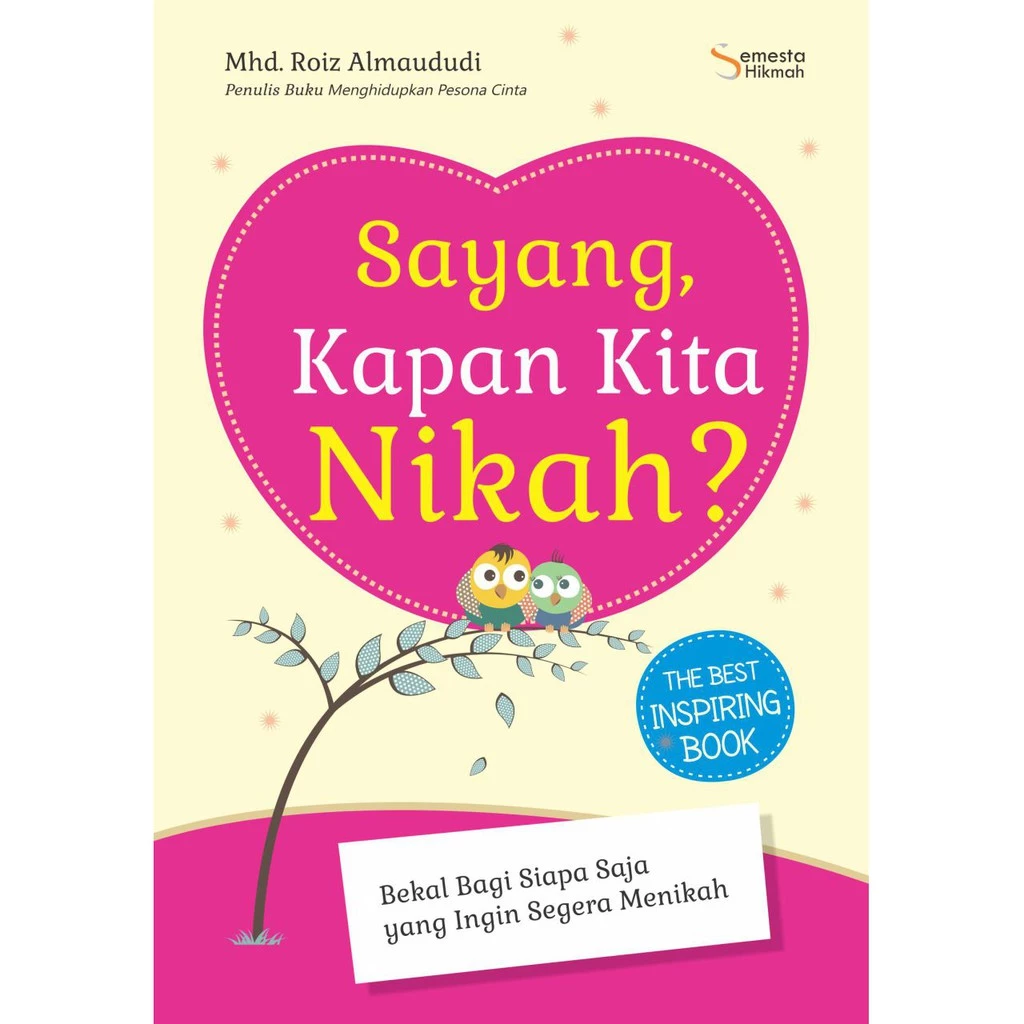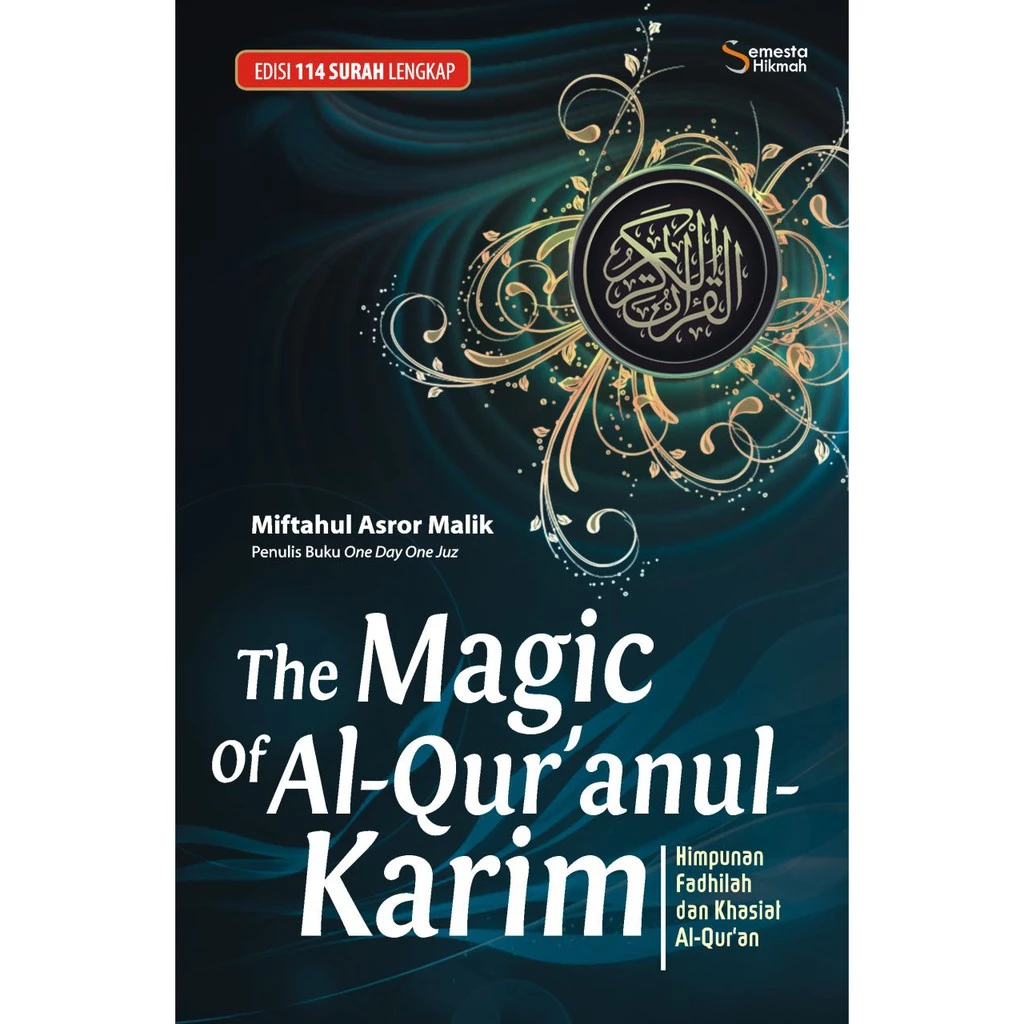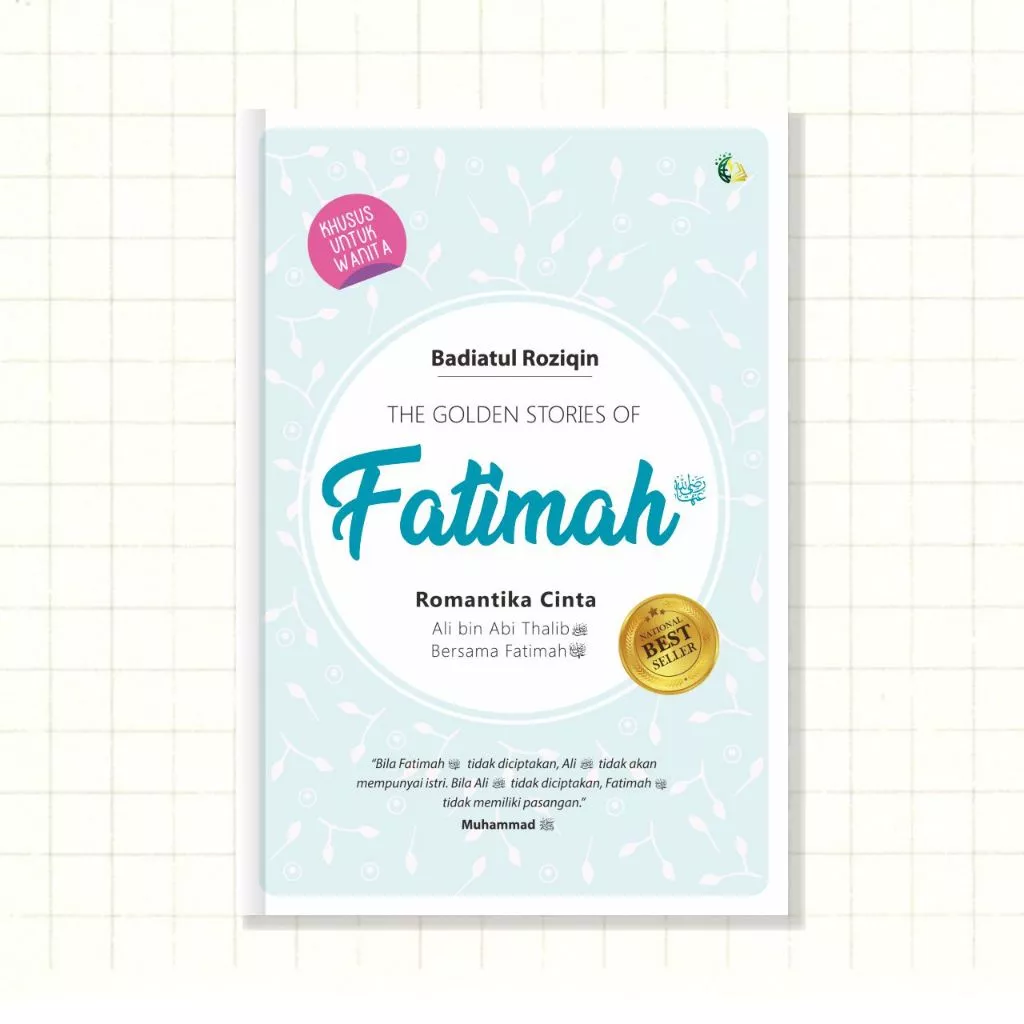Harmonisasi Kedokteran dan Fikih
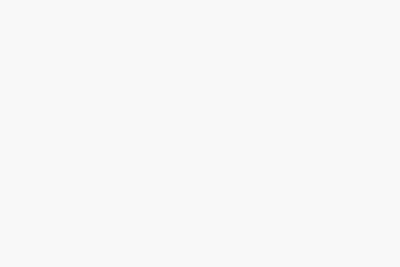

Abusyuja.com – Selain memiliki implikasi erat dengan Maqashid Syariah, ilmu kedokteran juga memiliki keakraban dengan fikih. Beberapa rumusan fikih tentang hukum halal-haram realitasnya cukup banyak dipengaruhi oleh aktivitas kedokteran.
Misalnya, jika sesuatu dinilai medis sebagai hal yang membahayakan, maka fikih bisa saja mengharamkannya. Begitu juga sebaliknya, jika sesuatu dinilai tidak membahayakan atau mengandung mafsadah, maka kemungkinan besar fikih juga tidak melarangnya.
Kontribusi dunia medis dalam fikih bukanlah hal yang aneh. Terkadang, yang bisa menentukan kadar “bahaya” adalah para dokter, bukan fukaha (ulama ahli fikih).
Ada banyak rumusan hukum fikih yang keputusan akhirnya masih menunggu pertimbangan dunia medis. Seperti contoh yang akan kami paparkan berikut:
1. Masalah Air Mussyammasy
Air Mussyammasy adalah air yang dipanaskan di bawah terik matahari secara langsung. Jenis air ini adalah salah satu permasalahan yang lumrah dijumpai dalam kitab fikih, khususnya mazhab Syafii.
Kajian kedokteran membuktikan, jenis air ini berada dalam wadah bejana tembaga atau logam, dengan mencapai suhu tertentu, dan berada di daerah dengan suhu luar biasa, misalnya saja dataran Hijaz.
Maka, air tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit kulit apabila digunakan untuk membasuh kulit ketika bersuci (misalnya). Meski tidak berdampak seketika, tetapi kulit akan mengalami kerusakan jika penggunaan air dilakukan secara intens dan dalam rentan waktu cukup lama. Hal ini bisa saja terjadi lantaran meningkatnya konsentrasi ion tembaga dalam air.
Lain halnya jika air yang terpapar sinar matahari tertampung dalam wadah yang tidak terbuat dari tembaga, misalnya bak semen atau plastik (tandon). Atau mungkin air sungai yang terpapar sinar matahari sampai suhu tertentu. Meskipun mencapai suhu yang sama sekalipun, penggunaan air ini tidak dimakruhkan.
Meski demikian, hukum yang terklasifikasi oleh ulama tentang air jenis ini tidak lepas dari keterkaitan penilaian ahli kedokteran. Jika penilaian dampak buruknya hanya sebatas “dugaan” kuat, maka hukumnya makruh. Tetapi, jika sudah “diyakini” menimbulkan mudarat atau penyakit, maka hukumnya haram.
Dalam kitab induk Al-Umm, Imam Syafii berkata,
“Aku tidak menghukumi makruh pada air yang terpapar panas matahari kecuali melihat dari sudut pandang kedokteran” (Al-Umm, Juz 1, halaman 16)
2. Penentuan Aib Nikah
Satu hal yang mendasar diberlakukannya akad nikah adalah untuk menyambung garis keturunan. Sebuah rajutan sakral antara anak dengan orang tuanya, berlanjut kepada kakeknya, dan seterusnya.
Islam begitu gigih memberikan dorongan bagi para pemeluknya untuk memperbanyak keturunan. Tujuannya supaya garis yang telah dimulai oleh leluhurnya tidak putus begitu saja.
Bahkan pada beberapa kasus, ketika ada pasangan yang tidak bisa melahirkan keturunan dikarenakan “penyakit” tertentu, mereka diperkenankan untuk bercerai.
Penyakit yang tervalidasi oleh ulama ada dua macam. Syekh Sulaiman al-Bujairami mengklasifikasikannya menjadi dua, penyakit menular dan tidak menular. Kesemuanya mencakup tujuh penyakit, yaitu lepra, gila, kusta, impotensi, terpotong habisnya alat kelamin pria, rutaq (Jawa: budug, atau buduken), dan qarn (tumor tulang pada bagian alat vital perempuan).
Konsekuensinya, kedua pasangan berhak melayangkan gugatan cerai secara sepihak, dengan ditangani oleh hakim. Tentunya dalam hal ini, dibutuhkan dua orang saksi yang membidangi dunia medis. Tugasnya untuk memberi putusan, apakah pasangan yang dituduh benar-benar mengidap penyakit yang tergolong “aib nikah” atau tidak.
Jalan keluarnya, dua orang dokter yang adil (memenuhi kriteria menjadi saksi), dimintai melakukan riset dan uji terhadap pasangan tertuduh, apakah benar ia mengidap penyakit atau tidak. Jika terbukti, maka mereka dituntut untuk bersaksi dalam persidangan. Sehingga dari kesaksian tersebut dapat dikeluarkan sebuah keputusan berdasarkan fakta yang ada.
3. Keabsahan Transaksi Tunawicara
Ijab-kabul memiliki posisi sakral dalam ranah fikih. Ia bisa dikatakan selalu hadis hampir dalam setiap babnya. Bahkan menjadi salah satu syarat esensial pada berbagai permasalahan, tak terkecuali dalam aktivitas muamalah. Misalnya, jual beli, nikah, talak, hibah, dan masih banyak lagi cabang persoalan yang berkaitan dengan akad.
Keberadaan ijab-kabul sangatlah penting, karena suatu akad bisa saja dihukumi tidak sah tanpa adanya ikrar ijab-kabul. Misalnya, pernikahan tidak bisa dihukumi sah apabila mempelai laki-laki tidak segera atau enggan menjawab apa yang dilayangkan penghulu.
Begitu juga dalam transaksi jual beli. Tidak sah hukumnya apabila yang bertransaksi tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai penjelmaan “kerelaan”. Begitu juga dengan talak, talak tidak akan jatuh jika suami hanya mengucapkan “cerai” dalam hatinya, tanpa dilafalkan dalam lisan.
Akan tetapi, ulama tidak tergesa-gesa memberi justifikasi ketika dihadapkan pada persoalan orang yang memang tidak sanggup berikrar atau berbicara karena suatu halangan tertentu.
Mungkinkah transaksi dianggap tidak sah bagi seorang tunawicara yang tidak mampu mengucapkan ikrar ijab-kabul yang posisinya menjadi syarat penting dalam transaksi? Atau justru sebaliknya?
Dalam persoalan ini, Imam Mawardi menuturkan, andaikan tunawicara disebab karena suatu penyakit, bukan bawaan sejak lahir, maka keabsahan setiap transaksinya ditentukan oleh para ahli bidang medis.
Jika dokter memvonis bahwa penyakitnya tidak bisa disembuhkan, maka legalitas transaksinya sama seperti orang yang bisa sejak lahir. Transaksinya tetap sah dengan cukup mengganti bahasa lahir dengan bahasa isyarat. Namun jika penyakitnya divonis bersifat sementara dan bisa sembuh, maka segala bentuk akad yang ia lakukan hukumnya tidak sah sampai ia sembuh.
4. Manusia dengan Alat Reproduksi Ambigu
Ada jenis kelamin yang populasinya sangat sedikit, yaitu kelamin ganda atau memiliki alat reproduksi ambigu. Fenomena ini bukanlah hal yang baru terjadi. Sejak dahulu sudah ada manusia-manusia yang terlahir dengan kelamin semacam ini.
Tanda seksualnya pun tidak dapat ditentukan, ada yang salah satu dominan, ada juga yang kedua-duanya dominan. Dalam istilah fikih disebut sebagai Khuntsa Musykil. Khustsa artinya orang yang berkelamin ganda, sedangkan Musykil artinya ambigu atau membingungkan.
Status “ambigu” ini pun akhirnya meluas sampai ke tatanan hukum fikih yang melekat padanya, mulai dari batalnya wudu karena menyentuh lawan jenis, batasan aurat, kebolehan menjadi imam salat, dan keabsahan nikah, semuanya seakan-akan menjadi mentah, apakah hukum yang melekat padanya disamakan seperti laki-laki atau perempuan.
Akan tetapi, dengan datangnya ilmu kedokteran, terasa ada cahaya yang terang akan permasalahan ini. Kedatangan dokter sebagai seorang ahli sangat membantu ulama fikih dalam upaya menentukan jenis kelamin yang tepat.
5. Ketetapan Had dan Kisas (Pembalasan)
Islam sangat menghargai kehidupan manusia. Seluruh anggota tubuh manusia sangatlah bernilai di mata Islam. Seperti tangan, kaki, telinga, hidup, bahkan sampai “darah” pun dinilai berharga. Sehingga, ketika ada hal-hal yang mengancam atau mencederai kemuliaan ini, agama akan merespons dengan tegas lewat penegakan hukum had atau kisas.
Akan tetapi, dalam penegakan hukum had dan kisas, para ulama sangatlah berhati-hati. Hal ini tergambar jelas lewat kerjasama mereka dengan ilmu kedokteran. Mulai dari penetapan batas-batas sampai pada kelayakan ditegakkannya hukum pidana had. Seperti pada permasalahan gigi anak kecil yang tercabut akibat perbuatan orang lain.
Dalam contoh di atas, vonis kisas berupa mencabut gigi yang sama dari tersangka, akan dijatuhkan setelah dokter memberi batas waktu tertentu. Waktu galib (umum/lumrah) untuk mengetahui tumbuh tidaknya gigi si korban. Selain itu, kisas wajib direalisasikan pada kerusakan-kerusakan yang bersifat permanen.
Itulah beberapa contoh persoalan fikih yang terlibat atau berhubungan dengan ilmu kedokteran. Memang benar, ilmu kedokteran sangatlah terlibat dalam pembentukan hukum fikih, meski tidak semuanya, paling tidak, ia mampu memberikan kontribusi signifikan di dalam beberapa kasus tertentu. Wallahu A’lam
Sumber:
Abd al-rahman bin Abi Bakr al-Syuyuti, Al-Asybah wa al-Nazair.
Muhammad bin Qasim al-Ghazali, Fathul Qari al-Mujib.
Abu al-Hasan ali al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir.
Muhammad bin Idris al-Syafii, Al-Umm.
Sulaiman bin Muhammad al-Bajayrami, Hasyiyah al-Bujayrami.
Ahmad bin Ahmad al-Qulyubi dan Ahmad al-Burullusi ‘Umairah, Hasyiyata al-Qulyubi wa Umairah.
Al-Hawi Al-Kabir
Dr. Mustafa al-Khan, Fiqh Manhaj ala Mazhab al-Imam al-Syafii.